Ketika Kedaulatan Terkangkangi di Pintu Masuk Udara RI, Siapa Bertanggung Jawab?
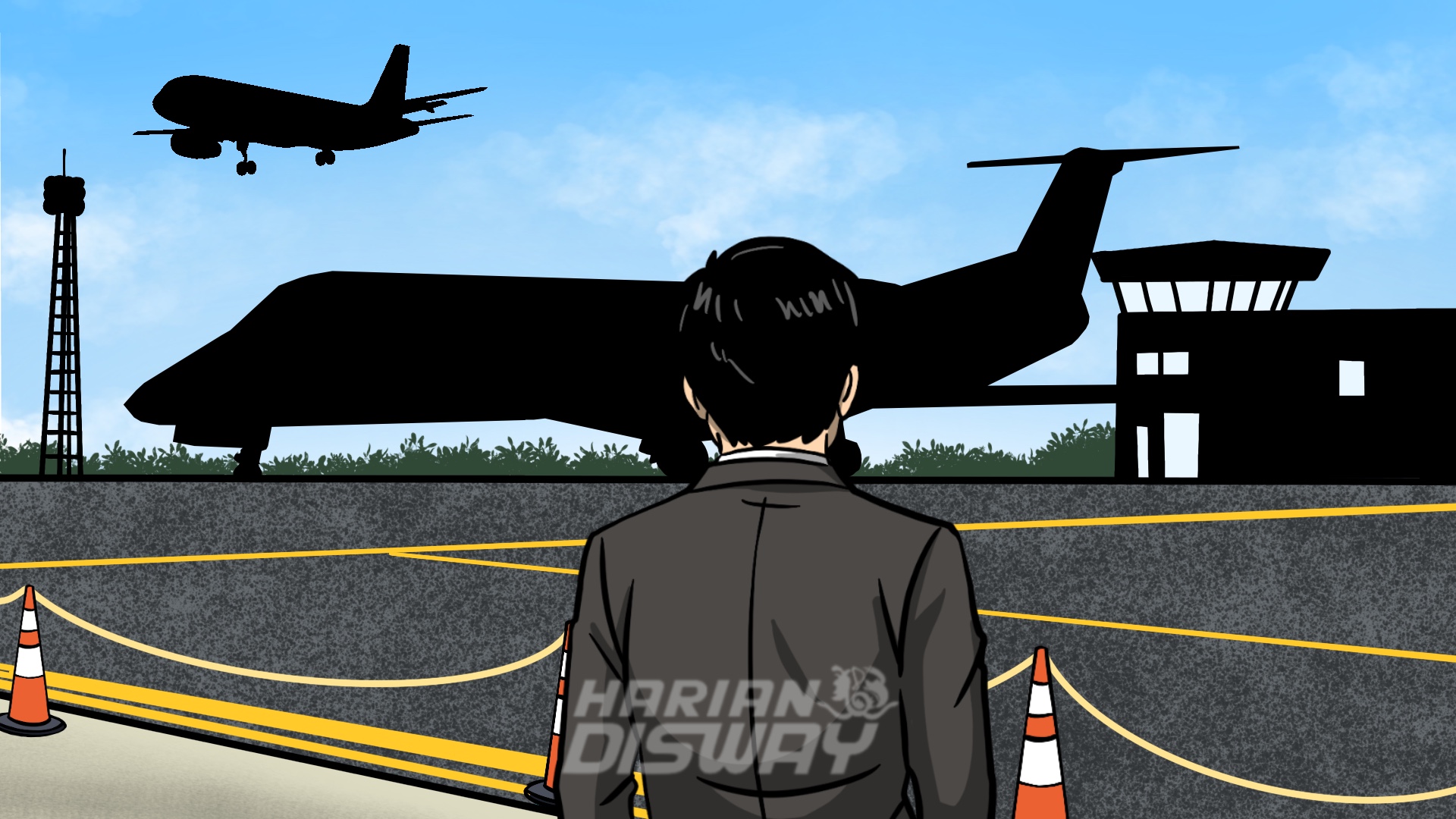
ILUSTRASI Ketika Kedaulatan Terkangkangi di Pintu Masuk Udara RI, Siapa Bertanggung Jawab?-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Kita hidup di era saat industri-industri besar sudah menjadi ”negara mini”. Mereka memiliki wilayah, ekosistem, tenaga kerja puluhan ribu, bahkan infrastruktur sendiri. Itu sah-sah saja. Selama negara tetap menjadi pemegang otoritas tertinggi.
BACA JUGA:Bandara Morowali Ilegal Beroperasi sejak 2019, DPR RI Bakal Panggil Kementerian Terkait
Namun, masalah muncul ketika kapasitas negara tidak berkembang secepat pertumbuhan industri. Ketika industri membangun lapangan terbang dan negara hanya ”mengikuti” prosedur yang sudah berjalan. Ketika fungsi pengawasan yang seharusnya tegas berubah menjadi sekadar formalitas, kita tak boleh diam.
Sebab, di sanalah letak persoalannya: negara menjadi kecil di hadapan korporasi besar. Padahal, hubungan yang benar adalah simbiosis yang diatur negara, bukan simbiosis yang mengatur negara.
Bagi saya, ini bukan hanya isu industri atau bisnis. Melainkan, ini isu yang mencakup keamanan nasional, perlindungan tenaga kerja, integritas data penerbangan, tata kelola transportasi strategis, dan kredibilitas negara di mata dunia.
Bandara adalah titik kendali. Di sanalah negara menegaskan dirinya. Ketika titik kendali itu kabur, kedaulatan ikut kabur.
SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Dalam bahasa pemerintahan modern, pertanyaan tersebut tidak ditujukan untuk mencari kambing hitam. Itu pertanyaan untuk memastikan bahwa negara bekerja sebagai satu tubuh, bukan organ-organ yang berjalan sendiri-sendiri.
Ada beberapa indikator kegagalan administrasi publik yang tampak dalam kasus ini.
Pertama, koordinasi lemah antara pusat dan daerah, antara Kementerian Perhubungan, pemerintah provinsi/kabupaten, hingga aparat keamanan.
Kedua, pengawasan yang pasif, seolah menunggu laporan, alih-alih membangun sistem deteksi dini.
Ketiga, fragmentasi regulasi, yaitu kewenangan tumpang tindih dan interpretasi peraturan tidak seragam.
Keempat, negara lebih reaktif daripada proaktif, padahal wilayah strategis tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kendali penuh.
Sebagai akademisi kebijakan publik, saya melihat itu sebagai contoh klasik regulatory capture, yaitu ketika negara terlalu percaya kepada operator, lalu kehilangan ketegasan sebagai pengendali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:














