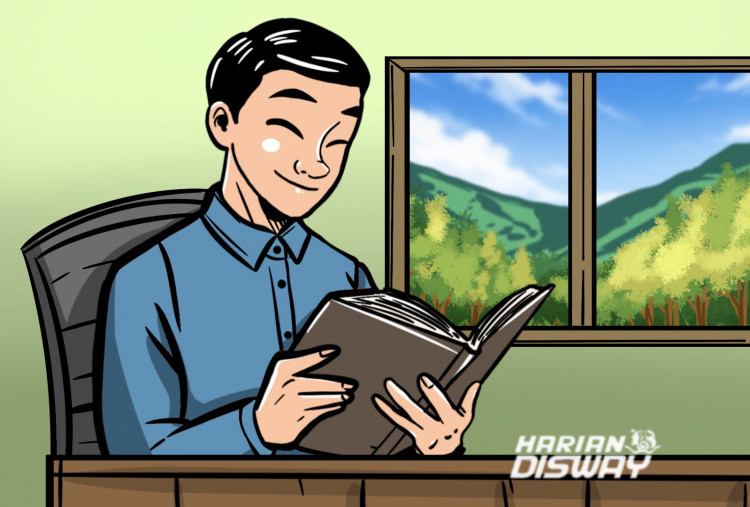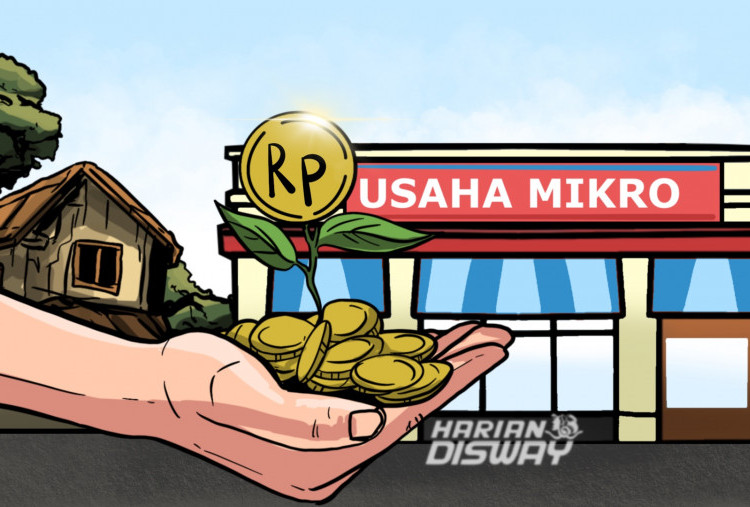Guru Besar hanya untuk Kampus Besar?

BEBERAPA waktu ini muncul polemik tentang pengangkatan guru besar atau profesor di perguruan tinggi di Indonesia. Polemik itu salah satunya dipicu oleh seorang dosen Universitas Indonesia, Dr Sri Mardiyati dari Fakultas MIPA, yang gagal menjadi guru besar. Dia lantas mengajukan gugatan terhadap Pasal 50 Ayat (4) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu tercatat dengan perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021.
Beberapa guru besar lainnya juga sudah menulis opini di media tentang polemik tersebut. Sebut saja seperti Profesor Iswandi Syahputra dari UIN Sunan Kalijaga dengan tulisan Membesarkan Guru Besar dan Profesor Bagong Suyanto dari Universitas Airlangga dengan tema Guru Besar yang Nyata. Keduanya merupakan guru besar dari perguruan tinggi besar. Saya sendiri belum menemui tulisan tentang isu itu dari sudut pandang dosen di perguruan tinggi kecil.
Mengapa kata perguruan tinggi kecil perlu saya sebutkan? Agar wacana tentang guru besar tersebut tidak hanya dimonopoli oleh perguruan tinggi atau kampus besar. Baik kampus besar negeri maupun kampus besar swasta.
Tulisan ini bukan bermaksud untuk mendikotomi kampus besar dan kecil. Sebab, harapan untuk menjadi guru besar tidak hanya menjadi cita-cita dosen di kampus besar. Pun para dosen di kampus kecil yang biasanya adalah swasta.
Cita-cita menjadi guru besar merupakan puncak karier seorang dosen. Menjadi guru besar tidak hanya terkait faktor prestise tetapi juga faktor kesejahteraan. Walaupun sebagian orang dengan malu-malu menyangkal faktor-faktor tersebut.
Di sini, saya mencoba sedikit melihat beberapa kendala dosen di kampus kecil dalam pengajuan guru besar. Permasalahan beratnya adalah mengumpulkan angka kredit terutama dari bidang penelitian. Selain permasalahan administratif tentunya.
Peluang di Kampus Besar
Dosen dari kampus besar apalagi kampus negeri lebih berpeluang besar untuk cepat menjadi guru besar dibanding dengan dosen dari kampus kecil. Itu karena di kampus besar biasanya terdapat program doktoral. Sehingga, banyak dosennya yang telah memenuhi syarat bisa menjadi promotor atau ko-promotor bagi mahasiswa doktoral tersebut.
Hal itu kan menguntungkan bagi dosen pembimbing tersebut. Sebab, biasanya mahasiswa S-3 akan diwajibkan atau paling tidak sangat dianjurkan untuk menulis artikel ilmiah di jurnal internasional yang bereputasi.
Kewajiban itu bisa jadi sebagai salah satu syarat ujian atau bahkan menjadi SKS tersendiri, dengan mencantumkan pembimbingnya sebagai salah satu co-author. Mahasiswa tersebut juga harus mencantumkan afiliasi lembaga tempatnya mengambil studi. Bukan lembaga tempatnya mengabdi sebagai dosen. Tentunya hal itu sangat menguntungkan bagi lembaga tempat mahasiswa studi tersebut, baik untuk kepentingan akreditasi program studi atau untuk penambahan angka kredit dosen pembimbingnya.
Hal yang menguntungkan tersebut tentu tidak dialami oleh para dosen dari kebanyakan kampus kecil. Di kampus kecil biasanya tidak terdapat program doktoral. Bukan karena tidak mau, tapi sulit persyaratan pendiriannya. Alhasil, para dosen dari kampus kecil itu kalau mau menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi harus berjuang mati-matian. Baik pikiran, tenaga, dan biaya. Tidak bisa ’’mendompleng’’ tulisan mahasiswa doktoral seperti di kampus besar.
Perbedaan Insentif Menulis
Sebetulnya peluang untuk menjadi guru besar, baik di kampus besar dan di kampus kecil, sama secara aturan. Namun, ada beberapa faktor internal yang menjadikan peluang menjadi guru besar di kampus besar lebih besar dan cepat dibanding peluang di kampus kecil.
Contohnya, di kampus besar biasanya ada dana riset internal selain dari Ristekdikti yang nilai nominalnya cukup bagi dosen untuk melakukan penelitian. Kampus kecil kerap tidak punya dana riset untuk dosen internal. Seandainya ada, itu pun belum cukup untuk mendanai penelitian yang target output-nya adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: