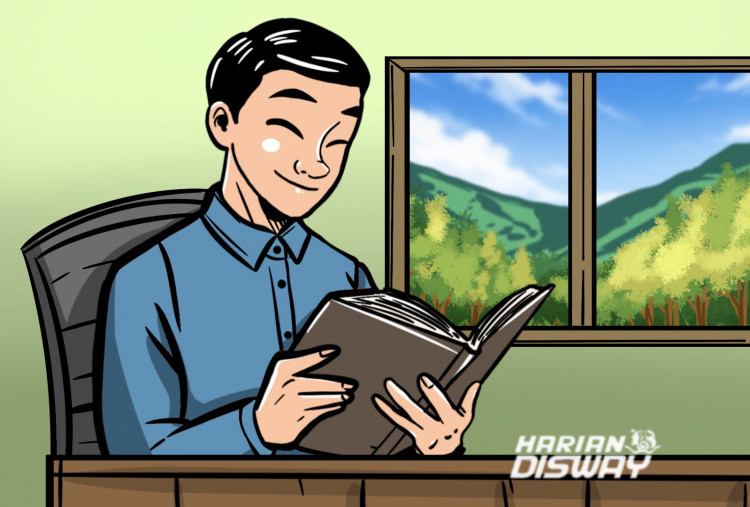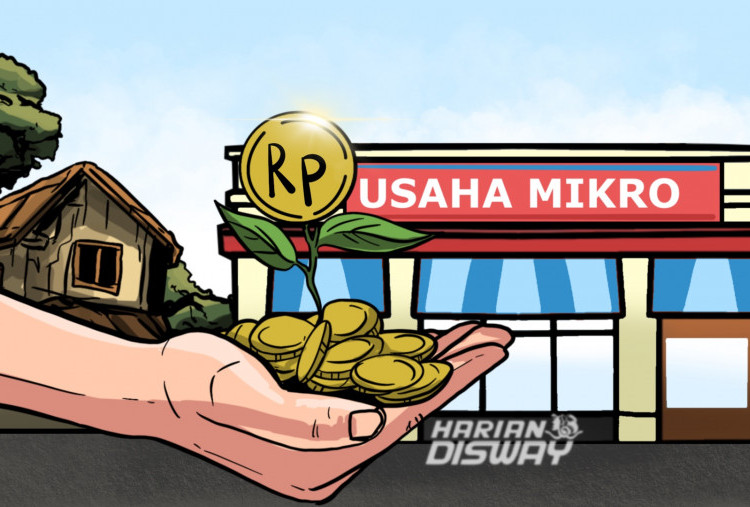Rambut Putih Surat Ijo

-Ilustrasi: Reza Alfian Maulana-Harian Disway-
MASSA yang mayoritas sudah lansia menggeruduk kantor DPRD Surabaya. Kain putih terikat di kepala mereka yang sudah penuh uban itu. Tertulis HAPUS SURAT IJO.
Saya menyaksikannya pada pertengahan 2016. Baru enam bulan jadi wartawan di DPRD Surabaya. Apa itu surat ijo? Sebagai pemuda yang besar di Gresik, istilah itu terasa sangat asing bagi saya.
Seorang lelaki berdiri di atas mobil pikap dengan berkacak pinggang. Di bagian bak mobil itu terdapat speaker jumbo yang diarahkan ke kantor wakil rakyat. Hujatan demi hujatan tertuju pada pemkot dan DPRD.
Rupanya mereka sudah berjuang puluhan tahun. Tuntutan tak pernah dikabulkan. Banyak yang menangis. Terutama ibu-ibu di barisan depan. Mereka membawa poster berisi tuntutan ini dan itu.
Sampai di sana saya masih belum ngeh. Apa itu surat ijo? Saya bertanya ke seorang wartawan senior yang juga meliput demonstrasi itu. ”Ah, biasa. Sejak zaman Soeharto gak mari-mari masalahe broo (Masalah tidak kunjung selesai, Red),” kata wartawan yang kini sudah almarhum tersebut.
Jawabannya tidak membantu sama sekali. Saya masih belum paham apa itu surat ijo.

Salman Muhiddin- Wartawan Harian Disway-Gambar Reza-
Satu jam berlalu. Mereka masih bertahan di bawah terik kemarau Surabaya. Sejumlah petugas pengamanan dalam (pamdal) yang tidak tahan dengan cuaca panas memilih berteduh di pohon-pohon kecil di dekat pagar depan.
Tak lama kemudian, seorang anggota DPRD Surabaya keluar menemui pendemo. Kalau tidak salah, hanya sepuluh perwakilan yang boleh masuk ke ruang komisi A.
Dari rapat itu, pertanyaan tentang surat ijo akhirnya terjawab. Rupanya ini masalah konflik agraria. Besar sekali. Melibatkan 48,2 ribu rumah yang dihuni ratusan ribu warga. Belakangan jumlahnya dikoreksi jadi 47,6 ribu persil. Mereka harus bayar PBB plus retribusi karena tanahnya diakui sebagai aset pemkot. Tak bisa jadi hak milik meski ada yang menghuninya turun-temurun sejak Indonesia belum merdeka.
Bisa jadi ini konflik agraria terbesar di Indonesia. Saya jadi tertarik mempelajarinya. Saya bertemu dengan berbagai tokoh surat ijo. Mulai Mantan Bupati Lamongan Moch. Faried yang tinggal di Surabaya, Endung Sutrisno, hingga Bambang Sudibyo.
Saya juga belajar banyak dari mewawancarai Prof Dr H Eko Sugitario, sang guru besar ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya). Atau almarhum Dr Taufik Iman Santoso yang juga pakar hukum dari Ubaya. Sebelum meninggal, Taufik berjuang mati-matian untuk meluruskan apa yang telah dilakukan ayahnya: Raden Soeparno, wali kota Surabaya 1974–1979.
Di tahun itulah sistem retribusi izin pemakaian tanah mulai berlaku. Taufik mendapat banyak cerita dari ayahnya bahwa sistem yang kelak dikenal sebagai surat ijo itu memiliki banyak kejanggalan.
Perjuangannya untuk meluruskan kebijakan bengkok itu kini diteruskan warga yang bergabung di grup Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS). Harijono yang jadi macan demonstran ada di pucuk pimpinan. Ia didukung Rachmat Musa yang jadi sekretaris jenderal. Mereka punya ribuan anggota yang begitu solid.
Dalam dunia jurnalistik, berita yang menyangkut banyak orang adalah berita menarik. Karena itulah, saya masuk makin dalam mengawal surat ijo.
Sampai suatu ketika seorang pejabat pemkot bertanya. ”Tanahmu sing endi (yang mana, Red)?” katanya dengan nada menyudutkan.
Kalimatnya terngiang-ngiang. Karena sering nulis surat ijo, saya dikiranya bagian dari para pejuang itu. Yang sudah sepuh-sepuh itu.
Tapi, kini saya jadi paham mengapa ia mengeluarkan kalimat itu. Mungkin pemkot juga lelah. Masalah surat ijo kok tidak ada habisnya. Seperti tidak ada solusinya. Mengapa "dosa" masa lalu itu dintanggung pemkot yang sekarang?
Kisah Dimulai dari Daendels
Akhirnya saya menemukan buku Reforma Agraria Setengah Hati: Pengelolaan dan Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya, 1966–2014.
Yang menulis almarhum Sukaryanto dari Unair. Ada kisah panjang di balik salah satu konflik agraria terbesar di Indonesia itu. Yang kalau diurut, bisa mundur hingga era kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1808–1811).
Nama Daendels sudah banyak disebut di buku-buku sejarah sejak sekolah dasar. Peninggalannya juga masih ada dan dirasakan sampai sekarang: Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang menghubungkan ujung timur dan barat Jawa. Dari Anyer sampai Panarukan.
Proyek ambisius sepanjang lebih dari 1.000 kilometer itu ia selesaikan dalam setahun (1908). Ia menyadari, konektivitas antarkota di Jawa adalah kunci penting pembangunan Hindia Belanda.
Belanda memperkuat Pulau Jawa sebagai basis militer sekutunya: Prancis. Sekaligus mempertahankan daerah koloni dari pasukan Inggris di kawasan Samudera Hindia. Jalan Raya Pos itu dibangun untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang.
Rupanya, akar permasalahan surat ijo bisa ditarik dari proyek itu. Anggaran pembangunannya sangat besar. Opsi tercepat untuk mendapatkan uang tersebut adalah menjual tanah pemerintah ke pihak ketiga. Yang kemudian dikenal sebagai istilah partikelir (swasta).
Tanah partikelir itu tidak hanya di Surabaya. Di Jakarta, Bandung, dan Semarang juga ada. Cuma, yang masih jadi persoalan dan tidak pernah selesai hanya ada di Surabaya.
Di dalam buku itu, Sukaryanto menampilkan peta Surabaya era penjajahan Belanda. Sumber aslinya buku H.F. Tillema, Kromoblanda. Terdapat arsiran di peta itu. Yang kalau dilihat secara kasatmata menunjukkan bahwa separuh Surabaya dikuasai partikelir atau tuan tanah.
Pemilik tanah punya hak pertuanan. Yang bisa menyewakan tanah ke penduduk. Mirip negara dalam negara.
Penduduk yang menyewa wajib mengolah tanahnya, plus membayar ke tuan tanah. Itulah akar sistem sewa tanah yang kemudian diperhalus dengan istilah retribusi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Rupanya, cara Belanda diteruskan setelah Indonesia merdeka.
Mulanya sistem retribusi berjalan lancar karena harganya terjangkau. Namun, ketika memasuki era Reformasi (1999), surat ijo jadi masalah. Warga yang dibungkam selama Orde Baru mulai melawan.
Sebagian besar penghuni tidak lagi patuh pada peraturan yang berlaku. Bahkan, timbul solidaritas komunitas warga pemukim tanah surat ijo yang kemudian membentuk organisasi massa berkekuatan besar.
Mereka meyakini bahwa sistem surat ijo penuh dengan kecurangan. Warga yang tinggal lebih dari 20 tahun seharusnya bisa menyertifikatkan tanahnya setelah reforma agraria dari UUPA. Separuh penghuni surat ijo yang sadar telah dicurangi memboikot pembayaran retribusi.
Fakta lain muncul. Warga yang berjuang melalui komisi informasi mendapatkan SK HPL 1997 yang jadi landasan pemkot mengeklaim aset surat ijo. Di salah satu diktumnya disebutkan bahwa pemkot harus memastikan tidak ada warga yang menempati tanah itu. Kalau ada persil yang ditinggali warga, areanya harus dihapus dari peta HPL. Atau pemkot harus mengganti rugi tanah dan bangunan warga itu.
Tahapan tersebut tidak dilalui. Surat ijo masih berlaku sampai sekarang di tahun 2022. Namun, para pejuang surat ijo tak lelah mencari keadilan. Mereka berjuang dari parlemen kota, provinsi, sampai menembus sejumlah kementerian hingga kantor presiden.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil bahkan pernah memberikan atensi khusus pada surat ijo. ”Pemerintah serius sekali bicara surat ijo. Kalau ada surat merah juga kita selesaikan,” katanya, membawa harapan.
Sayang, masa jabatannya berakhir sebelum menuntaskan persoalan surat ijo. Sang menteri kelahiran Aceh Timur itu di-reshuffle. Posisinya digantikan Marsekal TNI Dr Hadi Tjahjanto Juni lalu.
Menteri boleh berganti, tetapi mimpi menjadi ”orang merdeka” di Kota Pahlawan tak akan padam.
Beberapa orang yang melawan sejak masa reformasi itu ternyata masih ikut demo. Bahkan, sampai pakai kursi roda. Rambut mereka memang makin putih. Namun, perjuangan demi anak dan cucu akan diteruskan sampai mati. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: