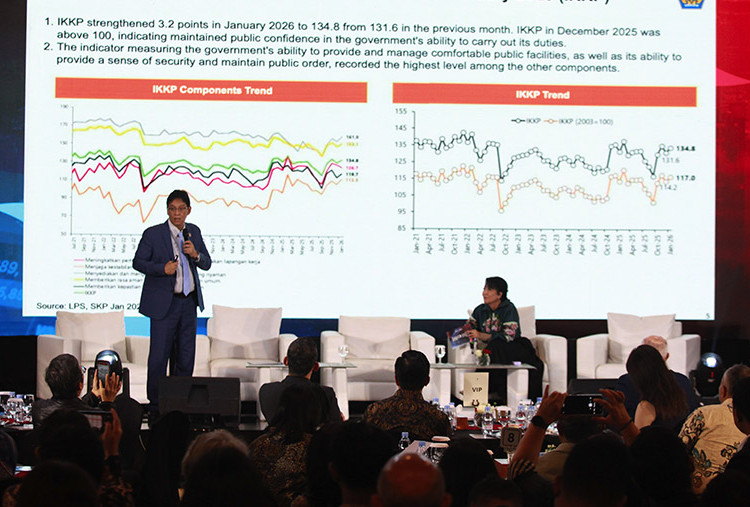The Undiscovered Self

Paslon ada yang harus menyiapkan diri untuk berkhotbah di gerbang ormas keagamaan. Apalagi yang mengundang itu para ulama yang “bertahta” menjadi tim. Sebuah penempatan yang membuat “luluhnya” batas-batas penganjur kebaikan dengan pembuat kebijakan. -HARIAN DISWAY-
MASA KAMPANYE capres-cawapres 2024 telah dilakukan dengan iringan yang gempita. Sorak sorai yang terwarnai dengan adu gagasan sampai utak-atik aturan debat kian mendebarkan. Panjatan doa dan memakai atribut keagaman semakin lazim adanya.
Peristiwa politik ini menjalinkan narasi yang sangat religius. Pihak yang selama ini getol agar tidak membawa-bawa identitas keagamaan dalam belantara politik tertindih sendiri. Paling tidak ini adalah babakan awal untuk tahapan penyadaran dalam kasunyatan yang menautkan dengan hormat mengenai relasi spiritual antara kekuasaan dengan kodrat-Nya.
Semua mengenakan atribut agama sambil meletakkan posisi untuk disebut paling peduli. Masjid dan gereja sebagai lambang keagungan yang menyematkan diri sebagai Rumah Tuhan harus disinggahi. Inilah kontestasi politik yang menyorongkan penanda bahwa agama hendak dibopong dengan takzim.
BACA JUGA: Darurat Iklim Memanggil Pemimpin Berkecerdasan Ekologis (1): Menuju Green Leadership
Paslon ada yang harus menyiapkan diri untuk berkhotbah di gerbang ormas keagamaan. Apalagi yang mengundang itu para ulama yang “bertahta” menjadi tim. Sebuah penempatan yang membuat “luluhnya” batas-batas penganjur kebaikan dengan pembuat kebijakan.
Capaian kedudukan sebagai tim sukses ternyata disambut dengan ungkapan alhamdulillah sangat keras dari sebuah ruangan kantor parpol dengan ketuanya yang menyunggingkan senyum seolah hendak menyatakan adanya kemenangan bagi dirinya.
Saya mendengarkan pengumuman tim sukses itu dalam hantaran yang menyisakan tanda betapa politik memang ada degub yang harus dibuncahkan. Pasangan yang diumumkan memang sama-sama seorang figur besar yang menyandang titel terhormat, ada gus, ada profesor dan penguasa kota.
Hanya saja yang satu melangkah dengan keyakinan yang tidak terkatakan. Sementara yang lain asyik dengan tariannya. Saat-saat seperti ini membentuk suatu labirin yang mengisahkan tentang diri yang adaptif atau hanya sekadar keberadaan tanpa makna. Parpol yang ragu kian kentara auranya.
Keputusan menampik dirinya sangat kentara dan dia pun bersikap untuk segera putar haluan dengan tekad menenangkan keluarga maupun handai taulan konstituennya. Begitulah yang dapat dikutip dari berbagai berita yang mewartakan apa yang menimpa dirinya.
Pada tingkatan tertentu akhirnya saya membuka kembali buku spesial The Undiscovered Self yang membanjiri pembaca di London tahun 2002. Buku yang dirangkum dari perbincangan bersama Carl Gustav Jung.
Ia psikiater berkebangsaan Swiss, pendiri mazhab psikologi analitis yang lahir di Kesswil pada 26 Juli 1875. Psikiater yang menyedot perhatian Sigmund Freud pendiri mazhab psikoanalisis. Buku ini sekarang mewarnai pustaka nasional sejak Februari 2018 dengan judul Diri yang Tak Ditemukan.
Pembaca akan tahu bahwa kebanyakan orang mencampurbaurkan makna “pengenalan diri” dengan pengetahuan yang dimiliki oleh ego-sadarnya. Siapa pun yang memiliki ego-sadar yang utuh dapat dipastikan mengenali dirinya sendiri. Tetapi ego hanya mengenal apa yang terkandung di dalam egonya. Bukan nirsadar tentang apa yang dikandungnya.
Orang-orang mengukur tingkat pengetahuan diri mereka dengan taksiran pemahaman yang dimiliki oleh lingkungan sosial tentang diri mereka. Bukan berdasarkan fakta batin yang nyata yang merupakan bagian terbesar yang tersembunyi dari mereka.
Dalam hal ini jiwa berfungsi sebagai tubuh yang memiliki struktur fisiologis dan anatomis. Meskipun ia hidup menyatu dengan struktur demikian. Namun, yakinlah hampir seluruh bagian dari struktur tersebut tidak pernah dikenal oleh pemiliknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: