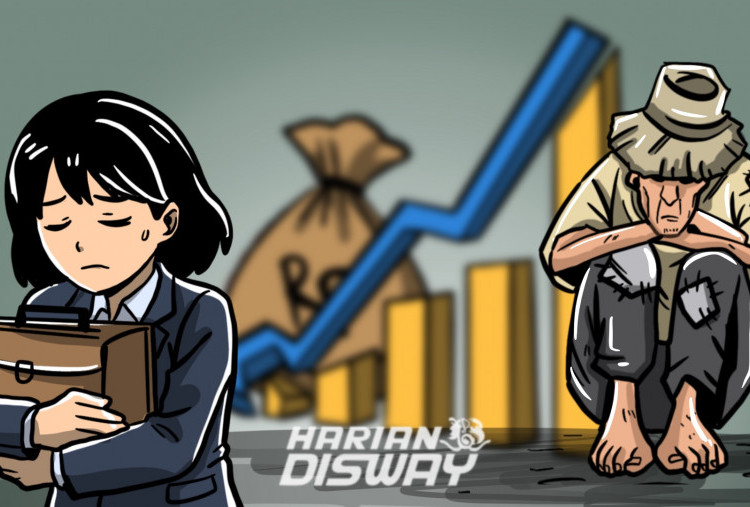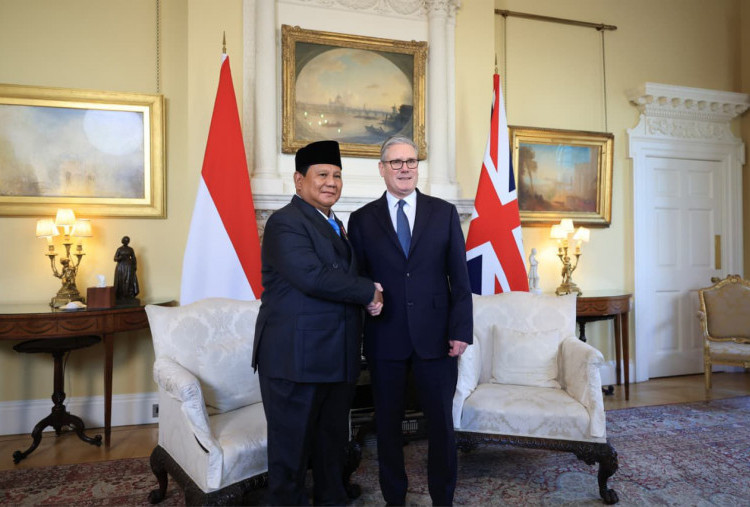Benarkah Orang Indonesia Paling Bahagia di Dunia?

ILUSTRASI Benarkah Orang Indonesia Paling Bahagia di Dunia?-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Namun, di sinilah masalah mulai muncul ketika istilah disederhanakan. Banyak media, dan bahkan pernyataan publik, mengganti kata flourishing menjadi ”paling bahagia di dunia”. Di sinilah kesalahan logika terjadi.
Sebab, di dunia riset kebahagiaan global, ada indeks lain yang jauh lebih populer dan sering dijadikan rujukan kebijakan internasional. Yaitu, World Happiness Report (WHR).
WHR, yang dirilis setiap tahun oleh PBB bersama University of Oxford, menggunakan pendekatan berbeda. Instrumen utamanya adalah cantril ladder: responden diminta menilai hidupnya sendiri dari angka 0 sampai 10. Dari tingkat ”terburuk” hingga tingkat ”sebaik-baiknya”. Sederhana. Subjektif. Langsung.
Hasilnya? Negara-negara Nordik –Finlandia, Denmark, Islandia– nyaris selalu di puncak. Sedangkan Indonesia? Faktanya, Indonesia jauh dari posisi pertama. Bahkan, sering berada di tengah atau bawah dalam konteks regional.
Apakah itu berarti orang Indonesia sebenarnya tidak bahagia? Belum tentu. Itu justru menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan konsep tunggal. Kebahagiaan itu punya banyak wajah.
WHR mengukur kebahagiaan dari: ”kepuasan hidup individual saat ini”, yang sangat sensitif terhadap pendapatan, layanan publik, keamanan sosial, dan efisiensi negara. Sedangkan GFS mengukur kebahagiaan dengan ”kualitas hidup manusia secara utuh”, yang sangat dipengaruhi oleh makna, relasi, dan nilai hidup.
Orang Indonesia mungkin tidak selalu puas dengan negara, birokrasi, atau ekonomi. Namun, mereka masih menemukan makna dalam keluarga. Masih merasa hidupnya ”ada gunanya”. Masih punya komunitas untuk bersandar. Dalam dunia yang makin individualistis, itu bukan hal kecil. Di sinilah kita perlu berpikir dan bersikap dewasa.
Mengatakan ”Indonesia paling bahagia di dunia” tanpa konteks adalah penyederhanaan berlebihan. Tapi, menertawakan hasil GFS juga keliru. Justru sebaliknya: GFS memberikan pesan penting tentang kekuatan sosial-budaya Indonesia yang sering diremehkan oleh indikator ekonomi semata.
Meski begitu, tetap jangan lupa, ada peringatan serius di balik kabar baik ini. Flourishing sosial tidak otomatis bertahan jika negara abai. Makna hidup bisa terdegradasi oleh ketimpangan.
Relasi sosial bisa rapuh jika keadilan dan hukum tebang pilih. Spiritualitas bisa berubah menjadi pelarian jika kesejahteraan struktural tak kunjung dirasakan.
Karena itu, hasil GFS seharusnya tidak dirayakan secara euforia, tetapi dijadikan cermin kebijakan. Negara perlu bertanya: bagaimana kekuatan sosial ini dijaga? Bagaimana makna hidup warga tidak dikorbankan oleh kebijakan yang teknokratis, tapi kering kemanusiaan?
Singkatnya, jawabannya begini: Benarkah orang Indonesia paling bahagia di dunia? Bergantung siapa yang bertanya, dengan alat ukur apa, dan untuk tujuan apa.
Jika bahagia diartikan sebagai hidup yang bermakna dan terhubung, Indonesia punya modal besar. Jika bahagia diartikan sebagai kepuasan hidup yang ditopang negara yang efektif, sepertinya itu pekerjaan rumah yang berat dan masih panjang.
Pun, justru dari situlah kebijaksanaan mulai diambil dan dilaksanakan dengan benar: tidak mabuk pujian, tidak pula minder oleh peringkat. Tetapi jujur dan objektif membaca diri sendiri.
Sebab, bangsa yang matang bukan bangsa yang paling sering disebut bahagia, melainkan bangsa yang tahu mengapa ia bisa bahagia, dan apa yang harus dijaga agar kebahagiaan itu tidak semu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: