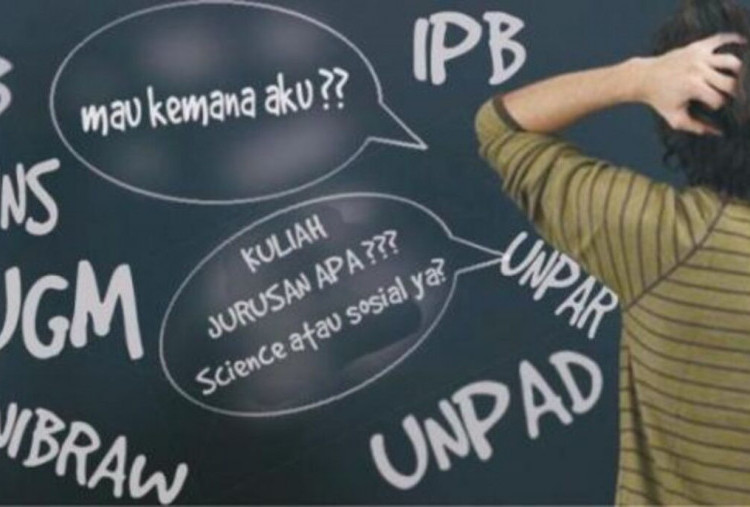Natal dan Agama Sains

-Ilustrasi: Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Mengapa harus demikian? Sebab, memang berbeda antara agama sebagai realitas teologis dan agama sebagai realitas sosiologis. Sebagai teologi, kebenaran mutlak bagi penganutnya. Agamaku agamaku, agamamu agamamu.
Sebaliknya, agama sebagai realitas sosiologis mengandaikan bahwa ekspresi dari keyakinan seseorang akan berbeda-beda. Karena nilai-nilai agama itu berkelindan dengan nilai-nilai yang telah ada. Itulah yang menyebabkan cara beragama orang juga berbeda.
Memahami agama sebagai realitas sosiologis memungkinkan kita untuk lebih menerima adanya perbedaan. Menjadikan kehidupan sosial sebagai panggung atas ekspresi berbagai nilai yang dianut umat manusia. Bukan sebagai dogma yang statis. Tapi, dogma yang dinamis.
Dalam kelompok Islam, masih ada yang berpandangan agama semata-mata sebagai teologi. Yang mengharuskan penganutnya untuk mengikuti dogma tanpa tawar-menawar. Sebagai nilai yang saklek. Sepenuhnya seperti saat agama itu diturunkan di muka bumi.
Paham itu berusaha menarik kembali ekspresi kehidupan beragama yang berkembang sekarang kembali ke ratusan tahun yang lalu. Berusaha menyamakan persis. Bahkan, sampai dalam hal berpakaian. Padahal, peradaban telah berubah sedemikian rupa.
Gus Muwafik, seorang penceramah agama dari Yogyakarta, memberikan penjelasan logis dengan ini. Ia meyakini, upaya menarik kembali umat Islam ke dalam peradaban zaman Nabi pasti akan menimbulkan benturan keras. Juga, pasti menimbulkan penolakan dari mayoritas.
Kenapa?
Sebab, peradaban umat ini sudah melaju ke depan. Seiring dengan perkembangan peradaban dunia. Ketika peradaban itu dipaksa kembali ke peradaban lama, akan terjadi tabrakan hebat. Seperti massa yang bergerak maju tiba-tiba dipaksa mundur kembali. Pasti akan chaos.
Belum lagi berbenturan dengan peradaban Barat yang lain sama sekali dengan Islam. Karena itu, menempatkan agama sebagai sains dan agama sebagai realitas sosiologis menjadi sangat penting. Agar agama, seperti disebutkan dalam teks, menciptakan rahmat bagi sekalian alam.
Misalnya, ada ustad yang mengharamkan dukungan kepada pemain bola yang beragama lain. Juga, mengharamkan pemain bola yang memakai celana pendek. Mereka jelas menafikan sepak bola sebagai bagian dari kehidupan masa kini dengan penonton terbanyak di dunia.
Kalau kita punya paham demikian, apakah Gus Dur dan sejumlah kiai yang hobi nonton bola termasuk golongan kafir? Padahal, kita tahu ketokohan dan keilmuan Gus Dur dalam Islam. Juga, kita tahu bagaimana kedalaman ilmu agama para kiai yang juga menggemari sepak bola.
Gus Dur punya cara menghadapi orang-orang yang suka mengafirkan lainnya karena perbedaan cara beragama. Ia bilang, gitu saja kok repot. Kalau dikatakan kafir, ya syahadat lagi. Demikian ia dengan entengnya menghadapi paham keras dalam beragama.
Seperti halnya peradaban dalam masyarakat pada umumnya, beragama pun akan mengalami tahapan-tahapan. Tahapan dalam cara memahami agama. Mulai tahap teologis, metafisika, dan ilmu. Tingkat pemahaman umat ini ditentukan tingkat ilmu agama mereka.
Yang berbeda barangkali dalam hal basis awalnya. Dalam beragama, seseorang memulainya dengan keyakinan teologis. Keyakinan yang diperoleh dari berbagai sumber teks. Baru bagaimana mereka mengekspresikannya tentang keyakinan itu dalam kehidupan sosial.
Cara beragama teologis menjadikan teks ajaran agama sebagai mitos-mitos. Segala apa yang terjadi di muka bumi ini mutlak karena Tuhan. Tak ada ruang campur tangan manusia. Kerusakan alam dan sosial selalu dimaknai sebagai azab atau hukuman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: