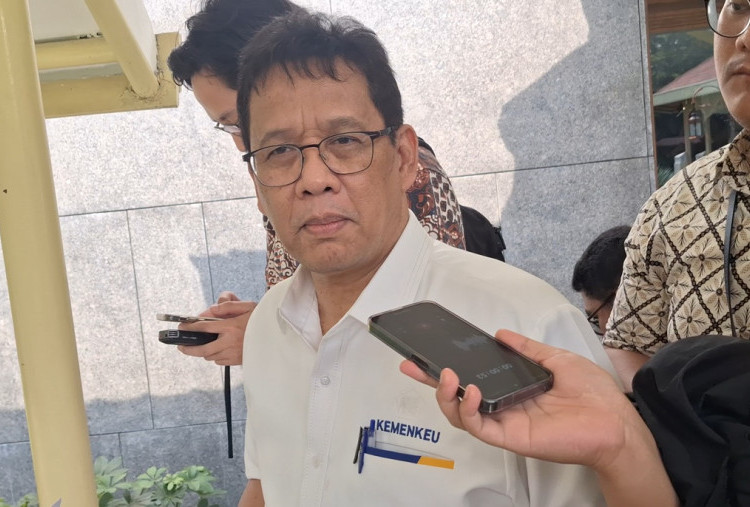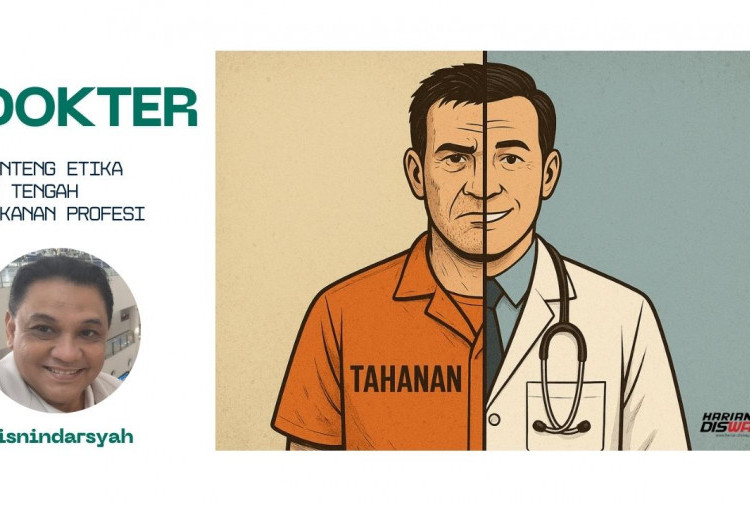Mewaspadai Ancaman Deindustrialisasi di Balik Pelonggaran Impor

ILUSTRASI Mewaspadai Ancaman Deindustrialisasi di Balik Pelonggaran Impor.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Jangan hanya karena gertakan AS, pemerintah Indonesia dengan mudah menyerah dan melonggarkan peraturan.
Kebijakan pemerintah seperti penghapusan kuota impor atau pelonggaran tarif seharusnya tidak dilakukan secara gegabah. Pemberlakuan tarif dan kuota yang tidak tepat takaran dapat menyebabkan distorsi impor.
Pun, perubahan kebijakan yang dilakukan tanpa memperbaiki distorsi tersebut dapat mengganggu upaya peningkatan kesejahteraan bangsa yang saat ini masih berlangsung.
Ketiga, kebijakan pelonggaran TKDN sangat riskan memperlebar banjir impor, mematikan industri lokal yang ujungnya mengakibatkan hilangnya lapangan kerja, dan menambah ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor.
Keempat, dalam jangka panjang, kebijakan relaksasi TKDN berisiko mempersulit upaya Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Ketakutan akan terjadinya deindustrialisasi kian menjadi kenyataan setelah Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menyampaikan rencana untuk membuka keran impor sebesar-besarnya. Ia mengatakan, siapa pun boleh membanjiri Indonesia dengan barang impor.
Itu menandakan bahwa kebijakan TKDN yang diyakini dapat meningkatkan permintaan produk domestik malah akan diotak-atik dengan membuka keran impor. Struktur industri substitusi impor di Indonesia masih bersifat infant industry (baru tumbuh berkembang).
Adanya kebijakan TKDN adalah melindungi industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Relaksasi keran impor sangat dicemaskan banyak pihak akan mematikan industri yang seharusnya mendapat prioritas tumbuh kembang.
Menurut hasil riset World Trade Organization (WTO) pada 2020, politik tarif secara historis cenderung menimbulkan efek balasan (retaliation), meningkatkan biaya produksi domestik, dan memicu inflasi.
Selain itu, International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa negara-negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap kebijakan tarif negara maju. Sebab, komoditas ekspor mereka bergantung pada harga, bukan inovasi.
Perang dagang AS-Tiongkok pada 2018-2019 telah menurunkan surplus ekspor Tiongkok dan memperburuk kinerja sektor manufaktur negara berkembang yang masuk rantai pasok global.
Demikian pula AS, kini harus menerima kenyataan bahwa imbas perang dagang yang dikobarkan mengakibatkan produsen dalam negerinya menjerit karena kelangkaan bahan baku impor dan mahalnya ongkos logistik yang harus ditanggung. Harga barang konsumsi dalam negeri terkerek naik (Feenstra & Sasahara, 2018).
Pada konteks itu, Indonesia yang juga terlibat dalam jaringan rantai pasok global sangat mungkin akan mengalami efek domino serupa.
Bukannya memanfaatkan peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi, pemerintah perlu menjadikan momen kali ini sebagai pemicu untuk memperluas basis dan tujuan baru ekspor dan memperkuat industri hilir agar lebih tahan terhadap guncangan global, dan bukan dengan relaksasi ”los dhol” terhadap masuknya barang impor yang justru antitesis dari semangat Astacita.
Dunia kini bergerak menuju tatanan ekonomi baru yang lebih kompleks dan penuh ketidakpastian. Dalam situasi itu, ketahanan dan kemandirian ekonomi bangsa akan menjadi penentu utama, apakah Indonesia dapat bertahan atau justru tumbuh lebih kuat. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: