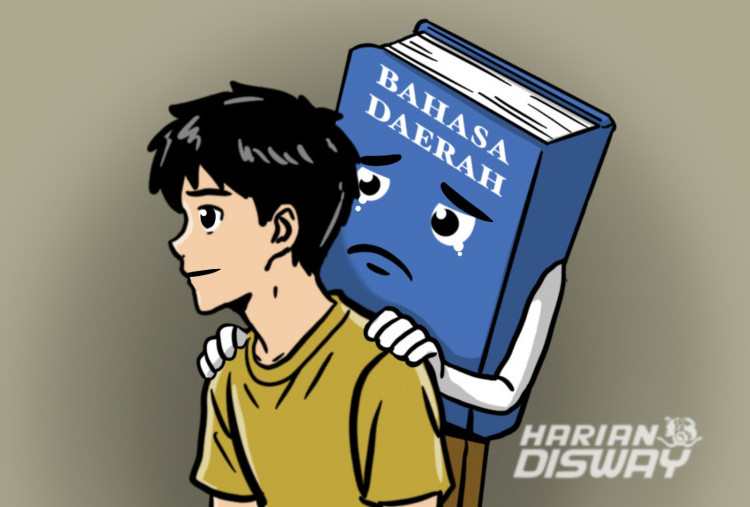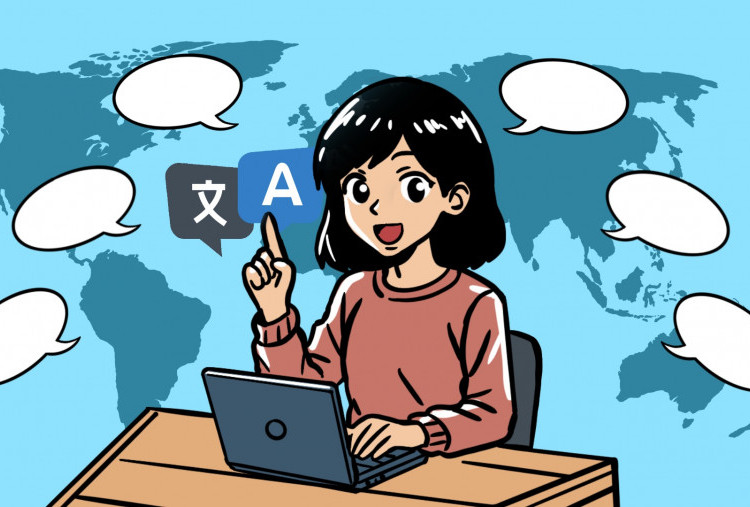Merawat Bahasa Daerah, Menjaga Identitas
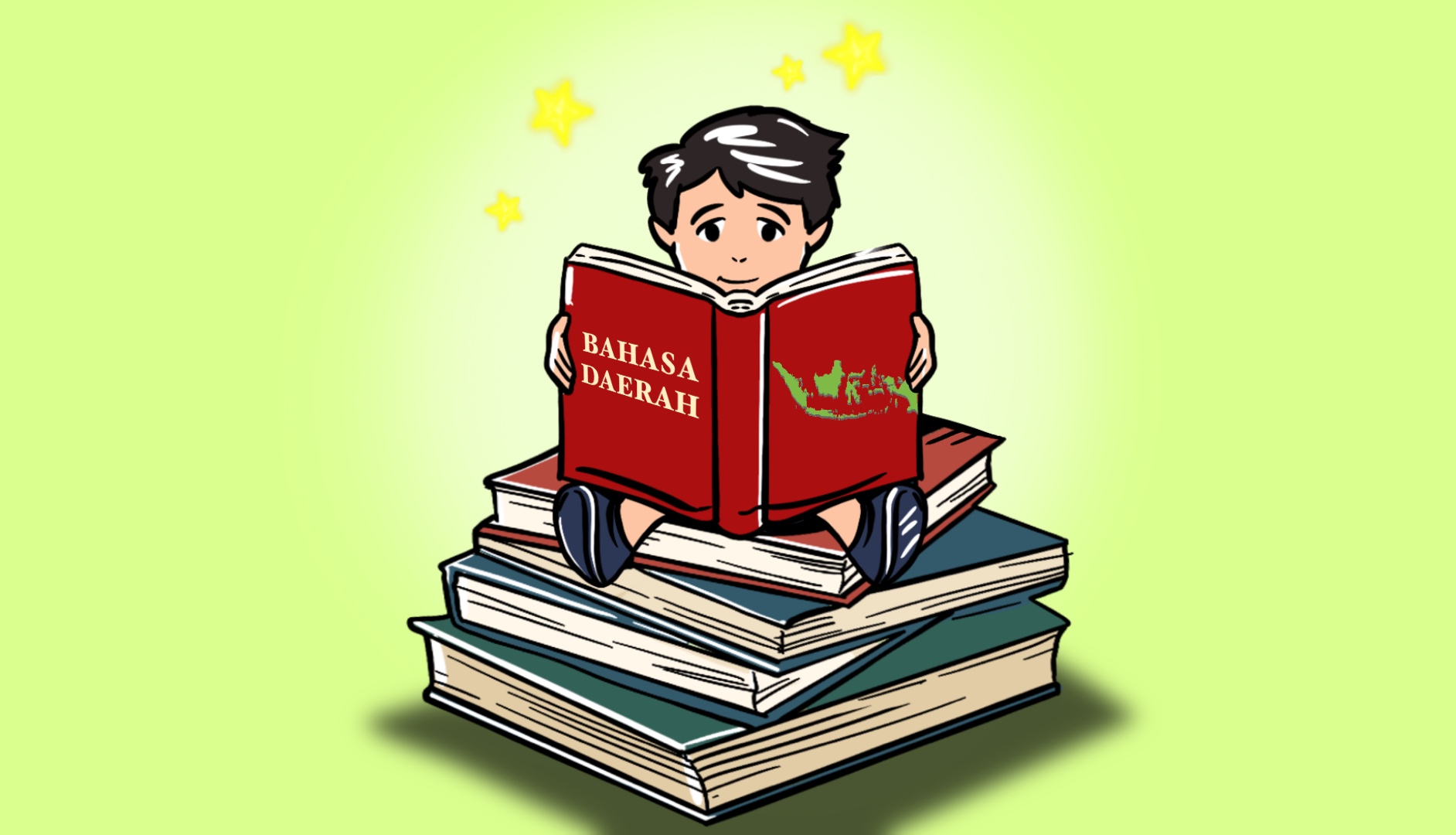
ILUSTRASI Merawat Bahasa Daerah, Menjaga Identitas.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Bahasa minoritas seperti bahasa-bahasa daerah di Indonesia, dengan jumlah penutur dan vitalits terbatas, tentu saja tidak terdeteksi dalam ekosistem tersebut. Sementara itu, mayoritas penutur muda (gen Z dan gen alpha), hidup mereka ada pada eksosistem digital.
Konsekuensi paradoks kebahasaan itu memang tidak mudah bagi upaya pelestarian bahasa ibu di Indonesia. Untuk mengatasi krisis tersebut, pendekatan multidimensi diperlukan karena ekosistem kebahasaan melibatkan lintas sektoral.
Peran dan program kementerian pendidikan dasar dan menengah melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk upaya pelestarian dan revitalisasi bahasa ibu selama ini harus diapresiasi dan harus tetap mendapat dukungan, walau arah dan pengembangan keilmuan Indonesia pada aspek STEM.
Upaya-upaya progresif yang dilakukan Badan Bahasa secara lintas sektoral selama ini melalui jalur formal terpusat berupa kebijakan pemerintah dan kurikulum sekolah, serta program dan kegiatan kebahasaan perlu disinergikan dengan pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta. Pemerintah sebenarnya memiliki instrumen hukum untuk melindungi bahasa daerah.
UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara secara tegas menyatakan bahwa bahasa daerah harus dilestarikan. Namun, implementasinya kerap terhambat oleh minimnya anggaran dan visi politik.
Di tingkat daerah, hanya segelintir pemerintah kabupaten yang serius mengintegrasikan bahasa ibu ke dalam program pembangunan.
Inisiatif yang dilakukan start-up lokal, komunitas, maupun lembaga swadaya masyarakat seperti Yototawa Media Center yang berkomitmen untuk melestarikan bahasa daerah Maluku perlu didukung dan digaungkan.
Pendekatan revitalisasi bahasa perlu dilakukan dengan mempergunakan budaya gen Z dan gen alpha yang lebih kasual, visual, dan akrab dengan teknologi. Teknologi harus menjadi alat afirmatif. Penyusunan data raya korpus bahasa daerah dengan akal imitasi yang diinisiasi Badan Bahasa perlu dituntaskan.
Kemitraan antara pemerintah dan platform digital bisa dimanfaatkan untuk kampanye pelestarian bahasa daerah. Di Selandia Baru, gerakan te-reo-maori yang dilakukan para pesohor dan digaungkan melalui media sosial seperti TikTok berhasil menarik minat generasi muda untuk kembali menggunakan bahasa Maori.
Bahasa Maori termasuk bahasa yang terancam kepunahan dalam daftar UNESCO. Penuturnya hanya 3 persen dari populasi dan hanya 2 persen dari etnis Samoa. Di Indonesia, kolaborasi serupa bisa dilakukan dengan melibatkan pesohor lokal dengan memanfaatkan potensi 167 juta pengguna aktif media sosial.
Lalu, bagaimana merajut harapan di tengah ancaman kepunahan? Jawabannya: keseimbangan. Bahasa Indonesia tetaplah pemersatu yang tak tergantikan. Tetapi, ia harus berjalan beriringan dengan penguatan bahasa daerah sebagai akar identitas.
Sementara itu, bahasa Inggris dan AI adalah jendela untuk membuka diri ke dunia. Keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk meminggirkan bahasa ibu.
Pada akhirnya, bahasa adalah cermin jiwa bangsa. Ketika bahasa Tandia punah, hilanglah cerita tentang suku Tandia yang pandai membaca jejak binatang di hutan Papua. Saat bahasa Kayeli lenyap, terkubur pula kearifan nelayan Maluku dalam menghormati laut.
Melestarikan bahasa daerah tidak berarti menolak kemajuan. Tetapi, menjaga agar Indonesia tidak kehilangan warna-warni kebudayaannya. Di era akal imitasi dan globalisasi mendikte cara kita berkomunikasi, merawat bahasa ibu sama dengan membangun fondasi yang kokoh untuk melompat ke masa depan. (*)
*) I.G.A.K. Satrya Wibawa adalah duta besar/wakil delegasi tetap Indonesia untuk UNESCO dan staf pengajar Departemen Komunikasi FISIP dan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: