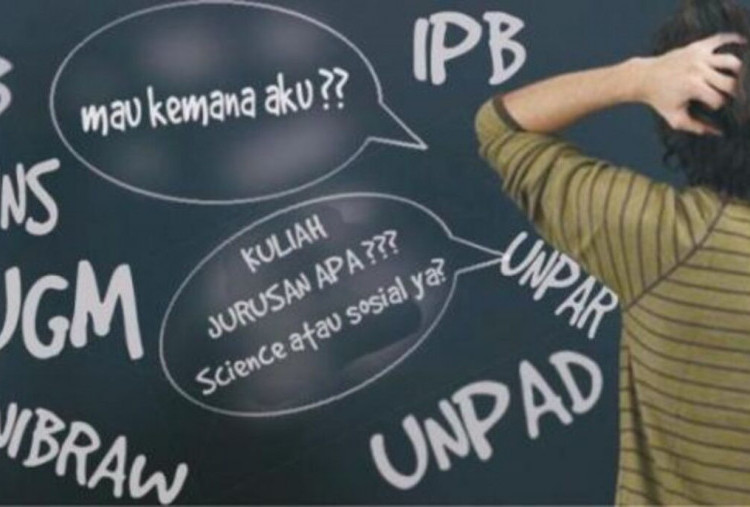Sound Horeg dan Kontestasi Moral Publik

ILUSTRASI Sound Horeg dan Kontestasi Moral Publik.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
BACA JUGA:Pengusaha Sound Horeg Setuju Diatur, Tapi Jangan Terlalu Ketat
EUFORIA JALANAN, EKSPLOITASI TUBUH, DAN KONTESTASI MORAL
Fenomena sound horeg tidak bisa dipandang sebatas dentuman musik yang memekakkan telinga, tetapi juga problem sosial yang menyingkap sisi gelap kebudayaan populer.
Di balik pesta jalanan yang digadang sebagai hiburan rakyat, muncul tarian erotis di ruang publik, sering kali menampilkan perempuan berpakaian minim di atas mobil terbuka, direkam, ditonton, bahkan disaksikan anak-anak.
Praktik itu tidak hanya melanggar etika, tetapi juga bentuk eksploitasi tubuh perempuan yang meneguhkan budaya patriarkal. Apa yang oleh Laura Mulvey disebut sebagai male gaze kini hadir telanjang di jalanan, lalu direplikasi tanpa henti melalui media sosial.
Konten yang awalnya lokal dengan cepat bermigrasi ke ruang digital global, sebagaimana diingatkan Nissenbaum (2004) melalui teori contextual integrity, menjadikannya rentan sebagai bahan voyeurisme dan pelecehan digital.
Dengan demikian, sound horeg tak hanya merusak ruang akustik, tetapi juga melahirkan lanskap visual yang berbahaya bagi perempuan dan anak-anak.
Kritik terhadap fenomena itu mencapai momentum ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan sound horeg haram.
Alasan yang diajukan menyentuh berbagai dimensi: dari kebisingan yang mengancam kesehatan, kerusakan moral akibat tarian vulgar dan konsumsi miras, hingga keterpaparan anak-anak pada tontonan yang merusak.
Polda Jawa Timur pun merespons dengan seruan resmi untuk menghentikan konvoi truk ber-sound horeg demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Slogan yang digaungkan lugas, ”utamakan kenyamanan bersama. Stop kebisingan yang meresahkan”.
Namun, di sinilah pro-kontra mencuat. Sebagian masyarakat menilai larangan itu sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan hilangnya ruang hiburan murah bagi rakyat.
Sementara itu, yang lain memandang langkah tersebut sebagai keharusan demi melindungi hak publik atas ketenangan, keamanan, serta nilai moral yang terjaga.
Pertarungan argumen itu memperlihatkan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar kebisingan fisik, tetapi juga benturan nilai: antara euforia kebudayaan populer dan norma etika yang hidup di tengah masyarakat.
Jika tidak dipertimbangkan dengan masak, kebijakan yang lahir hanya akan menimbulkan distorsi baru, di mana suara dentuman digantikan oleh konflik laten tentang siapa yang berhak menentukan batas hiburan dan moralitas.
SOLUSI TIDAK MELULU HARUS POPULIS
Apakah langkah penataan itu dapat dianggap sebagai represi terhadap budaya rakyat? Kami kira tidak. Justru sebaliknya, ia merupakan upaya menyelamatkan ruang publik dari kekacauan yang kerap dibungkus atas nama ”kebudayaan”.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: