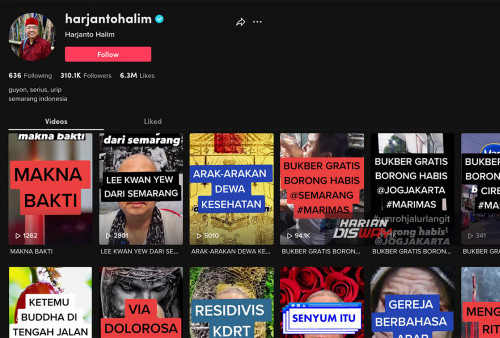Series Jejak Naga Utara Jawa (5): Melawan dengan Informasi

Azmi Abubakar menunjukkan papan nama sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan yang dikoleksinya.-Retna Christa-Harian Disway-
Azmi Abubakar membangun Museum Pustaka Peranakan Tionghoa sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma dan diskriminasi. Jurusnya adalah informasi.
KAMI memasuki Museum Pustaka Peranakan Tionghoa pada sebuah pagi yang gerah, Sabtu, 14 Januari 2023. Azmi Abubakar sendirian di dalam museum yang didirikannya 2011. Bayangannya tampak dalam ruangan yang masih temaram. Bergerak di antara lemari kayu dengan pintu kaca.
Museum tersebut tidak berdiri sendiri. Ia berimpit dengan bangunan lain dalam sebuah ruko di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Hanya ada papan nama bersahaja di depannya. Menghadap ke arah matahari terbit.
Begitu kami memasuki museum, aroma khas itu menyergap. Apak. Bau masa lalu. Seperti tumpukan kertas dari masa silam.
Itu wajar. Sebab, ada lebih dari 30 ribu koleksi yang disimpan Azmi di museum tersebut. Seluruhnya menggambarkan jejak perjalanan warga Tionghoa yang mendiami Nusantara. Jejak itu menjulur dan membentang ke berbagai hasil pustaka. Mulai koran, majalah, komik, atau kliping kesebelasan sepak bola yang berkiprah pada awal abad ke-20.
Di lemari utara, di bawah papan nama Kedai Kopi Ie Leubeue, misalnya. Ada kumpulan komik Panji Tengkorak. Itu adalah cerita silat bergambar besutan Hans Rianto Sukandi alias Hans Jaladara. Nama aslinya, Liem Tjong Han.
BACA JUGA: Geger Pecinan Sampai Orde Baru
Atau Put On, komik strip pertama di Indonesia, yang dulu terbit di majalah Sin Po. Put On adalah karya Kho Wang Gie. Isinya tentang Put On, bujang lapuk yang selalu bernasib malang. Dalam sebuah kisah, diceritakan Put On menyelinap keluar dari rumahnya karena disuruh menyapu dan mengepel. Ia pergi ke rumah Mintje, gadis pujaannya. Ternyata, Mintje pun sedang beres-beres rumah. Jadilah Put On kembali jadi jongos. Menyapu dan mengepel. Sial…
Tetapi, Azmi tidak membatasi diri pada karya-karya kuno. Yang terang, seluruh koleksinya adalah tentang kehidupan warga Tionghoa. Maka, di antara buku-buku yang mendiami lemari-lemari besar tersebut ada karya baru. Misalnya, Geger Pacinan 1740-1743; Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC. Buku itu terbit pada 2013. Penulisnya adalah KRMH Daradjadi Gondodiprojo.
Koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa milik Azmi Abubakar.-Yulian Ibra-Harian Disway-
’’Dulu saya memang tidak pilih-pilih. Yang penting ada huruf mandarin, ada bendera Indonesia,’’ tutur pria beranak empat tersebut.
Azmi memang tidak bisa berbahasa Mandarin. Apalagi membaca aksara hanzi. Maka, yang penting terasa ada unsur Tionghoa, ia ambil. Yang bisa berbahasa Mandarin justru anak Azmi. Yang akan kuliah ke Tiongkok. Di kota Nanjing lalu berlanjut ke Ningbo.
Dan yang dikoleksi Azmi bukan cuma buku. Ia juga mengumpulkan kartu nama pebisnis top yang pernah beken di zamannya. Misalnya, Liem Sioe Liong alias Sudono Salim. Atau Oei Ek Tjhong atau Eka Tjipta Widjaja.
’’Dari kartu nama ini saya tahu hal yang tidak banyak diketahui orang,’’ kata Azmi. Ia lalu menunjukkan sisi belakang kartu nama Eka Tjipta Widjaja. Di situ ada kepanjangan Bimoli. Ternyata, merek minyak goreng itu adalah singkatan dari Bitung Manado Oil Limited.
Di museum itu juga ada papan nama asli milik Tiong Hoa Hwee Kwan, sekolah khusus orang Tionghoa pertama di Indonesia. Berdasar sejumlah referensi, sekolah itu berdiri pada 1900. Jauh sebelum Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. ’’Sekolah ini juga mengancam Belanda,’’ ucap Azmi.
Untuk membendung pengaruh itu, Belanda mendirikan Hollandsch-Chineesche School. Sekolah Belanda-Tionghoa yang kali pertama didirikan pada 1908.
Museum Pustaka Peranakan Tionghoa juga memajang foto dr Sun Yat Sen, Bapak Negara Tiongkok Modern. Sun Yat Sen adalah penggerak revolusi Tiongkok yang akhirnya menumbangkan dinasti Qing. Kisah tentang Puyi, kaisar terakhir Negeri Panda itu, akhirnya diangkat menjadi film pada 1987. Judulnya, The Last Emperor.
Foto Sun Yat Sen dipajang komplet bersama motto sang pemimpin. Yakni, tian xia wei gong, tong zhi reng xu nu li, dan ge ming shang wei cheng gong. Artinya, dunia adalah milik semua orang, kita harus tetap bekerja keras, karena revolusi belum selesai. ’’Gara-gara ini, saya pernah dipanggil Koramil,’’ tutur Azmi. Tetapi, ia berhasil meyakinkan bahwa yang dipajangnya itu bukan ajaran komunis. Bukan hal terlarang.
Azmi tertarik dengan orang kebudayaan Tionghoa karena kiprahnya sebagai aktivis pada 1998. Ia menjadi saksi penjarahan dan kerusuhan yang terjadi pada pengujung Orde Baru tersebut. ’’Museum itu adalah bentuk ketidakterimaan saya pada peristiwa itu. Saya ikut terluka,’’ kata Azmi.
Peristiwa itu seperti menjadi puncak represi yang dilakukan rezim itu pada kalangan Tionghoa. Budaya dibatasi, aksara dan bahasa Mandarin dilarang, status kewarganegaraan banyak yang digantung.
’’Coba, kalau bukan karena kuasa Tuhan, mungkin kebudayaan mereka sudah hilang. Itu cultural genocide,’’ katanya.
Azmi adalah mantan Ketua Mahasiswa Aceh se-Nusantara saat kuliah. Nah, yang cukup menyentuh adalah ketika ia menyaksikan warga Tionghoa juga turut membantu korban Tsunami Aceh pada 2004.
Bagi Azmi, warga Aceh dan warga Tionghoa sama-sama mengalami tsunami. Yang satu adalah bencana alam, yang satu lagi tsunami regulasi. Karena itu, melalui museumnya, Azmi bertekad melawan tsunami yang telah beranak-pinak menjadi stigma. ’’Obatnya adalah informasi. Saya melawan dengan informasi,’’ ucap alumnus jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Indonesia, Serpong itu.
Dan kepingan-kepingan informasi itulah yang dikumpulkannya dengan tekun. Hingga mengisi lemari-lemari lawas di dalam Museum Pustaka Peranakan Tionghoa… (*)
*) Tim Harian Disway: Doan Widhiandono, Retna Christa, Yulian Ibra, dan Tira Mada.
SERI BERIKUTNYA: Harta Karun dari John Lie
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: