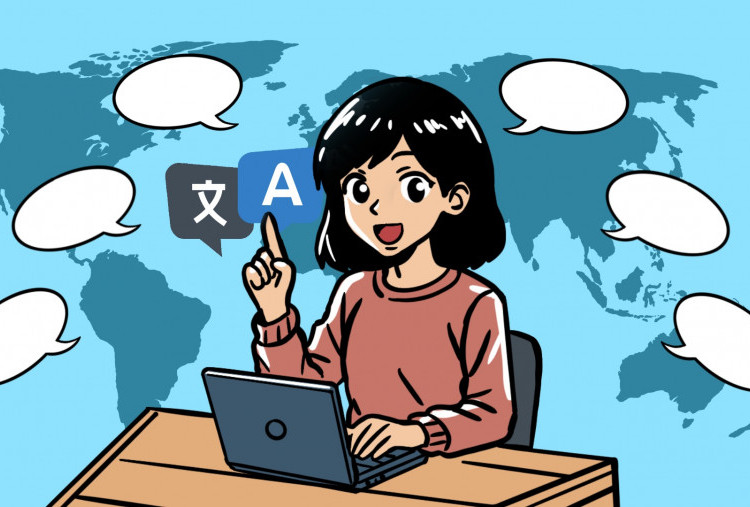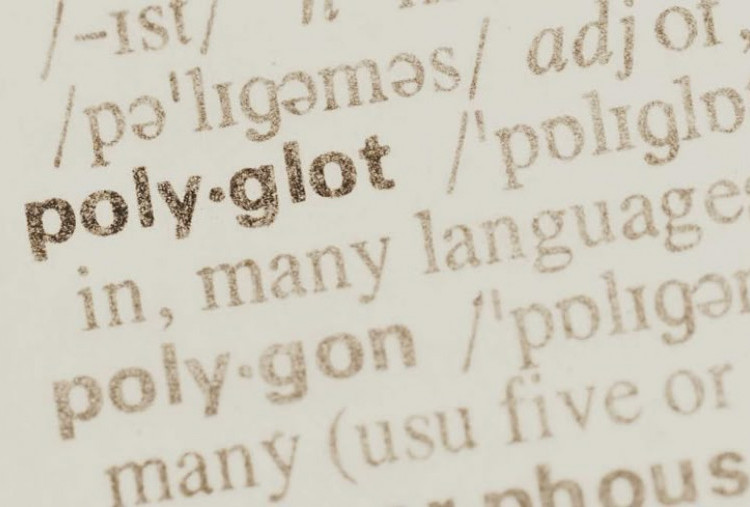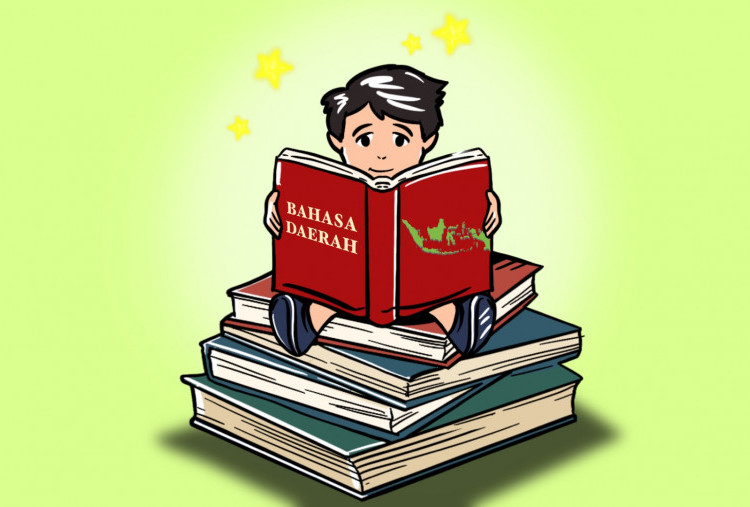Translanguaging, Identitas Bangsa, dan Trigatra Bangun Bahasa
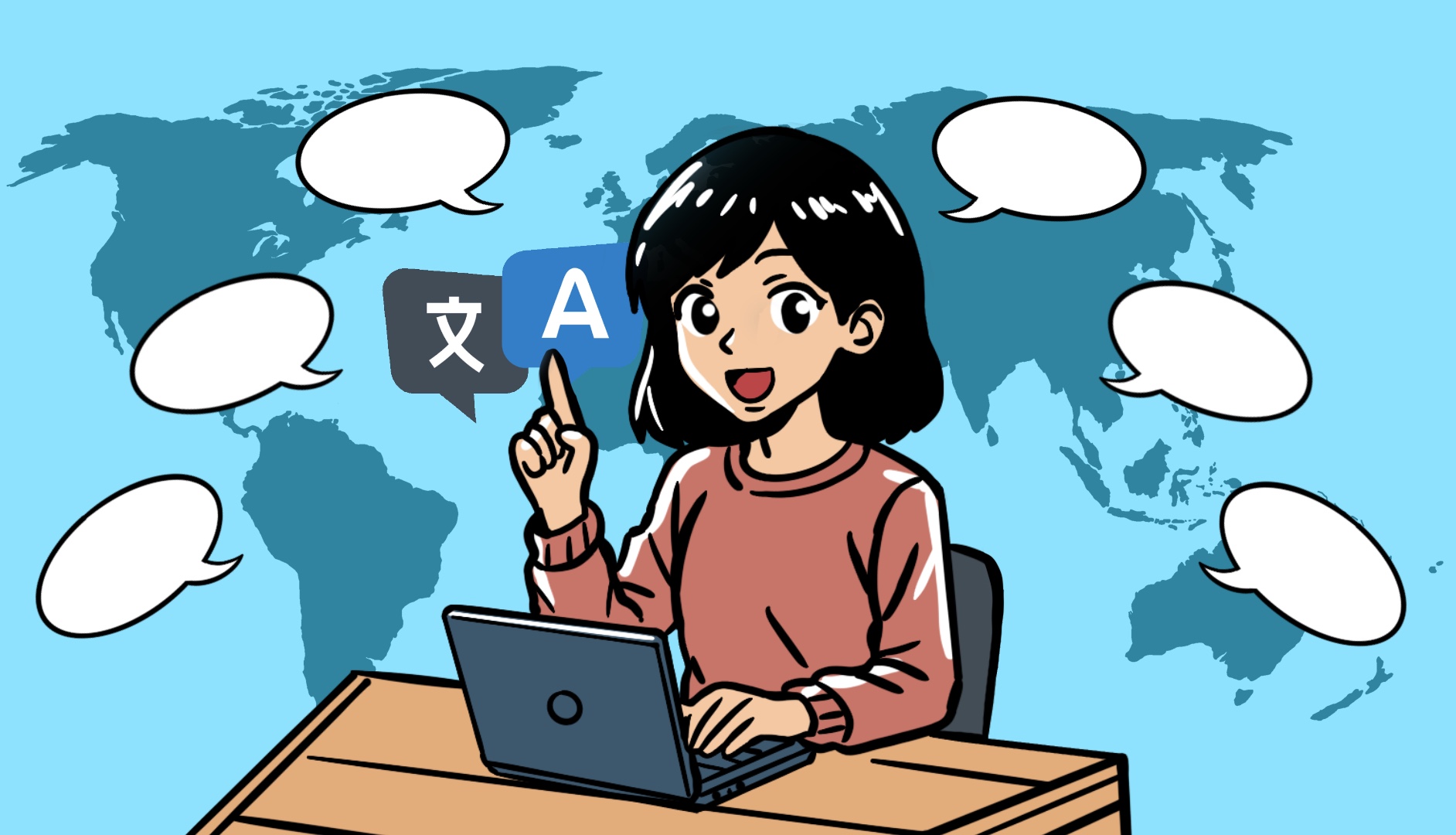
ILUSTRASI Translanguaging, Identitas Bangsa, dan Trigatra Bangun Bahasa.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Akibatnya, banyak sekali mitos yang beredar yang berisi kekhawatiran tidak mendasar di masyarakat yang menggiring asumsi bahwa pengguna multibahasa tidak akan pernah menguasai berbagai jenis bahasanya dengan sempurna.
Salah satu mitos adalah adanya anggapan bahwa ”jika anak-anak belajar bahasa lain sebelum menguasai bahasa ibunya, mereka akan kebingungan dan akibatnya baik kemampuan bahasa ibu dan bahasa lainnya (misalnya, bahasa Inggris) tidak akan sempurna”.
Keyakinan itu tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan. Faktanya, kita ketahui bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis. Sebab, kita akan senantiasa belajar tanpa henti (paling tidak dalam penguasaan kosakata yang terus berkembang).
Mitos itu dapat menghambat perkembangan praktik multikebahasaan masyarakat Indonesia. Misalnya, jika kita terus menunggu bahasa ibu kita sempurna, sampai kapankah kita akan belajar bahasa asing dan bahasa nasional?
Atau, ada sebagian masyarakat yang kemudian memilih untuk mengembangkan salah satu kemampuan bahasanya, bahasa Indonesia atau bahasa asing saja, karena takut jika mereka belajar bahasa lain pada saat bersamaan, hal itu akan memengaruhi penampilan kemampuan berbahasa mereka secara keseluruhan.
Mitos kedua yang juga dapat menghambat perkembangan praktik multikebahasaan adalah adanya kepercayaan bahwa jika kita belajar bahasa lain setelah dewasa, kita tidak akan pernah berhasil menguasainya dengan baik.
Penelitian tentang penguasaan bahasa kedua membantah mitos itu dengan memberitakan bahwa anak-anak maupun dewasa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam belajar bahasa.
Berhasil atau tidaknya praktik kebahasaan dalam keseharian kita ditentukan dari beberapa faktor seperti seberapa banyak kita menggunakan seluruh sumber daya komunikasi yang kita pahami secara efektif.
Misalnya, jika dalam keseharian kita lebih banyak berinteraksi dengan kolega multietnis di institusi tempat kita bekerja, kita akan cenderung lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa perekat antar-rekan kerja multietnis tersebut.
Pun, ketika anak-anak kita yang bersekolah di sekolah internasional lebih banyak berinteraksi dengan teman sekolah dan gurunya dalam bahasa Inggris, mereka juga akan lebih terbiasa dalam menggunakan bahasa tersebut.
Tidak heran bahwa terkadang di masyarakat urban seperti Surabaya kita sering jumpai anak-anak usia sekolah dasar yang fasih berbahasa Inggris, tetapi terbata-bata dalam bahasa Indonesia.
Faktor lain yang memengaruhi praktik kebahasaan dalam keseharian adalah adanya perkembangan teknologi yang memicu peningkatan penggunaan ponsel pintar. Kita dapat bebas berselancar di dunia maya menjelajahi berbagai komunitas digital, seperti gim daring dan media sosial, dengan menyeberangi batasan teritori fisik sebuah negara.
Hal itu membentuk cara komunikasi yang membaurkan bahasa dan variasinya, gambar, visual, simbol, dan unsur-unsur kebahasaan lain.
Cara komunikasi dunia digital seperti itu dapat menjelaskan fenomena bagaimana anak-anak kita yang aktif secara digital seakan lebih mudah memahami bahasa asing seperti bahasa Inggris daripada bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah mengingat bahasa Inggris memang lebih dulu dipakai di platform digital.
Mengacu kembali pada Trigatra Bangun Bahasa, lantas bagaimana seharusnya sikap kita dalam berkomunikasi? Apa yang dapat kita lakukan dalam mengatasi ketimpangan penggunaan kebahasaan itu?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: