Inklusivitas yang Masih Pincang: Catatan Kritis di Hari Disabilitas
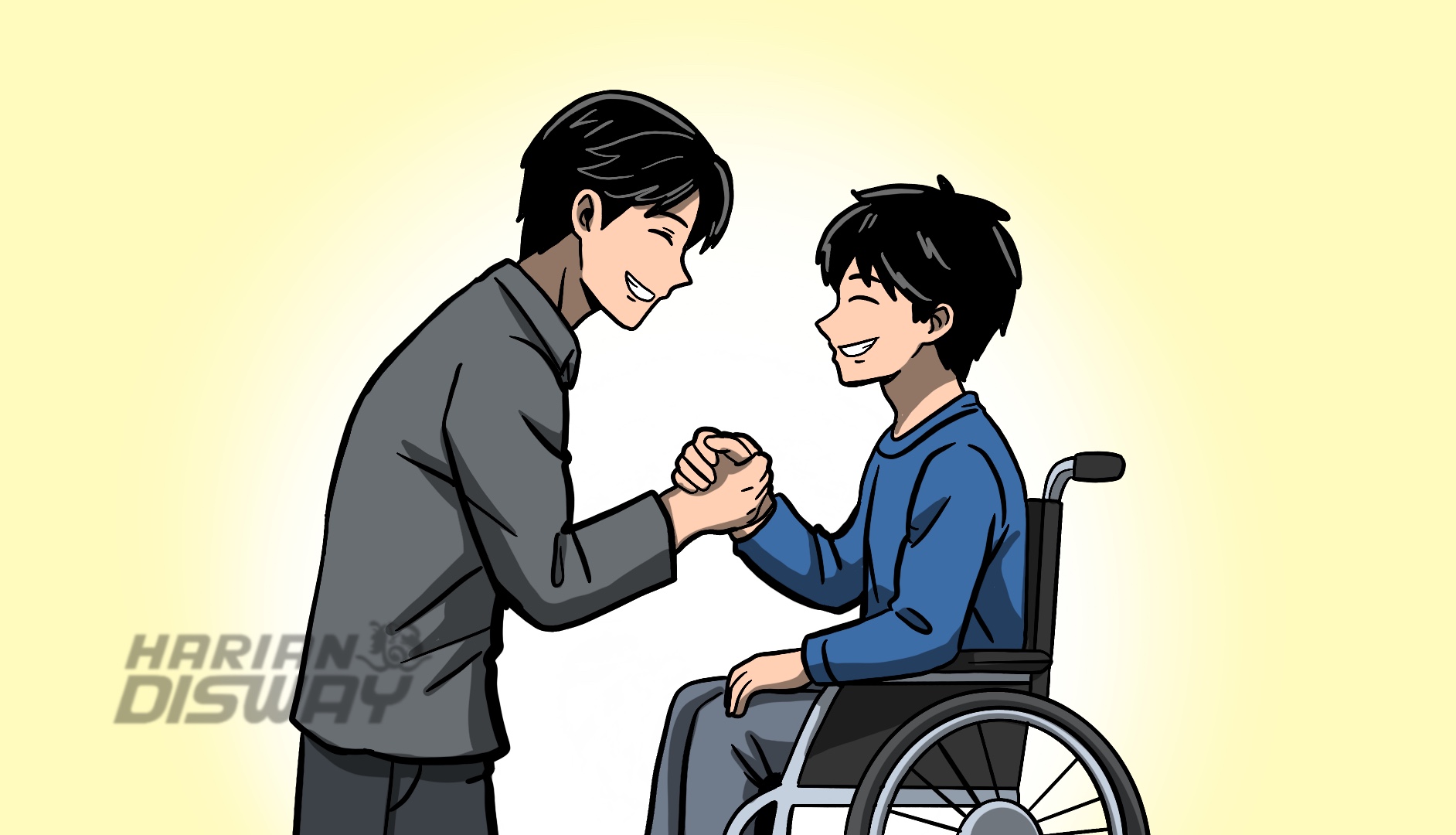
ILUSTRASI Inklusivitas yang Masih Pincang: Catatan Kritis di Hari Disabilitas.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
BACA JUGA:Komunitas Disabilitas Berkarya dan ACI Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022
Ableisme bekerja seperti rasisme dan seksisme. Ia beroperasi diam-diam, menciptakan batas-batas sosial yang membatasi peran dan kesempatan bagi kelompok disabilitas. Itulah mengapa diskriminasi terhadap disabilitas tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi berwujud kekerasan simbolis, yaitu penyingkiran yang dilembagakan dan dinormalisasi sehingga dianggap wajar.
Data BKKBN tahun 2021 mencatat 987 kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Namun, angka itu hanya puncak gunung es. Jauh lebih banyak kekerasan simbolis yang tidak tercatat.
Misalnya, pertama, kurangnya akses pendidikan yang inklusif. Kedua, minimnya pekerjaan yang menerima tenaga kerja disabilitas. Ketiga, kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan keragaman kebutuhan. Keempat, layanan kesehatan yang tidak ramah disabilitas.
Ketika akses pendidikan dan pekerjaan tidak tersedia, penyandang disabilitas dipaksa hidup dalam lingkaran eksklusi yang sulit diputus. Struktur sosial –bukan disabilitasnya– yang menghambat mereka berkembang.
BAHASA ISYARAT DAN KRISIS AKSESIBILITAS
Kasus pada penyandang tuli menjadi cermin paling jelas mengenai kegagalan sistemik negara menghadirkan akses inklusif. Bahasa isyarat seharusnya menjadi sarana komunikasi publik, tetapi realitas menunjukkan hal-hal yang anomali.
Pertama, rendahnya kesadaran publik (lack of awareness). Bahasa isyarat masih dianggap kemampuan tambahan, bukan kebutuhan sosial. Layanan publik jarang menyediakan interpreter dan simbol-simbol bahasa isyarat hampir tidak terlihat dalam ruang publik.
Kedua, minimnya penerjemah profesional (limited interpreter availability). Dengan lebih dari 223.000 penyandang tuli dan 73.560 penyandang bisu-tuli (Komnas Perempuan), Indonesia tidak memiliki jumlah interpreter yang memadai.
Penerjemah di sekolah, pelayanan kesehatan, atau acara resmi negara masih sangat terbatas.
Ketiga, ketimpangan kota-desa (regional disparities). Akses bahasa isyarat di kota besar relatif lebih baik, tetapi penyandang tuli di daerah perdesaan hampir tidak memiliki akses terhadap layanan komunikasi dasar. Itu menunjukkan bahwa inklusi disabilitas masih menjadi ”privilege urban”.
Bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi, melainkan hak yang fundamental. Ketika bahasa isyarat tidak tersedia, penyandang tuli kehilangan akses terhadap pendidikan, informasi publik, layanan darurat, hingga hak politik.
Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum kuat, yakni UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasinya lemah. Banyak kebijakan yang hanya berhenti pada tataran normatif tanpa mekanisme evaluasi yang jelas.
Beberapa masalah utama, yaitu aksesibilitas infrastruktur publik, masih rendah, pemenuhan kuota 2 persen tenaga kerja disabilitas di instansi pemerintah sering tidak tercapai, kurangnya data komprehensif yang diperlukan untuk membuat kebijakan berbasis bukti, dan minimnya anggaran khusus untuk program inklusif.
Regulasi tanpa implementasi hanyalah retorika. Negara hadir tidak melalui perayaan, tetapi melalui keberpihakan kebijakan. Penyandang disabilitas harus menjadi subjek publik-politik yang setara, tidak dimaknai berbeda dari segi kebijakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:













