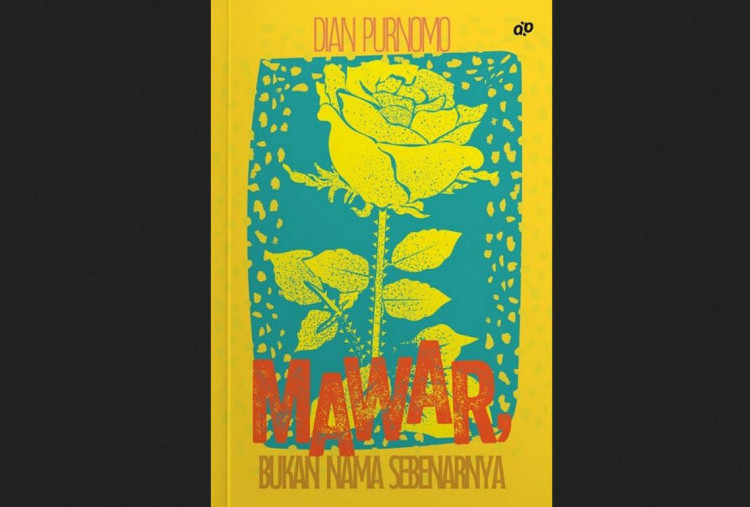Ulasan Buku Mawar, Bukan Nama Sebenarnya karangan Dian Purnomo: Ironi Perempuan di Negeri Patriarki
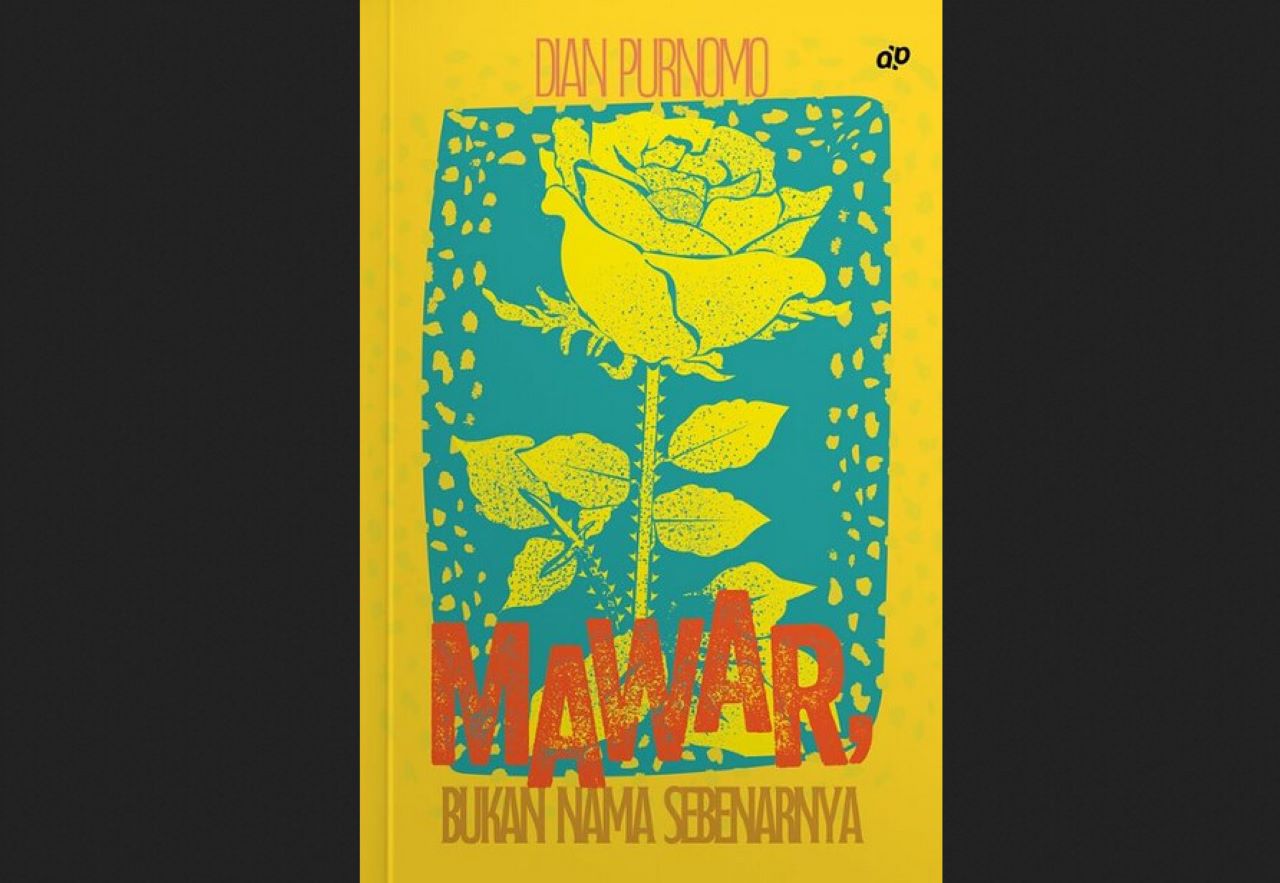
MAWAR, BUKAN NAMA SEBENARNYA menyuguhkan fakta betapa tidak mudahnya menjadi perempuan di negara yang dicengkeram patriarki.--goodreads
Melalui novel Mawar, Bukan Nama Sebenarnya, Dian Purnomo menyuguhkan segudang masalah perkawinan anak. Ironisnya, kisah fiksi ini terasa sangat nyata dan dekat dengan realita masyarakat Indonesia.
MAWAR masih sangat belia ketika harus memasuki mahligai rumah tangga. Dia dituntut dewasa sebelum waktunya dan dipaksa bertahan di tengah lingkungan yang terlalu keras untuk perempuan seusianya.
Nasib buruk Mawar lahir saat kesadaran dan empatinya tumbuh. Dunianya runtuh setelah dia memilih untuk membela martabat seorang teman yang menjadi korban pelecehan. Dia merasa sekolah tidak adil karena memilih absen dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, pihak sekolah merasa Mawar berlebihan. Sebagai siswa biasa, dia yang masih belia dianggap terlalu emosional menyikapi masalah yang “sepele” di mata sekolah.
BACA JUGA:Ulasan Memoar Aurelie Moeremans, Broken Strings-Kepingan Masa Muda yang Patah: Pecahkan Sunyi, Gugah Penyintas Jadi Berani
Relasi kuasa dan tekanan sosial membuat Mawar terpaksa putus sekolah. Melanjutkan hidup dengan stigma, jelas membuat kehidupan Mawar makin nelangsa. Namun, Mawar tidak menyerah.
Berlatar tempat di kawasan Puncak-Bogor, Mawar adalah potret pedih remaja perempuan yang dijebak tradisi dan budaya buta yang tak mengindahkan empati dan kemanusiaan.

GUSTI MADE AYU KAYIKA mengulas "Mawar, Bukan Nama Sebenarnya" dari kacamata perempuan yang sering tak didengarkan suaranya hanya gara-gara gendernya.--Dokumentasi Pribadi
Mawar dipaksa mengiyakan perkawinan anak, bekerja tanpa perlindungan kontrak, menjadi tulang punggung keluarga, dan hampir tidak pernah dipeluk keluarganya sendiri saat dia benar-benar membutuhkannya.
Mawar yang saat itu belum 17 tahun harus menjalani nasib yang dipilihkan sang ibu untuknya. Menikah di usia belia. Orang dewasa sering membebankan masalah keluarga pada anak perempuan hanya karena mereka bisa melakukannya atas nama kepatuhan. Padahal, mereka sedang mencelakakan sang anak.
BACA JUGA:Ulasan Film Judheg (Worn Out) dalam Rangkaian JAFF 2025: Kebodohan, Kemiskinan, dan Cinta Monyet
BACA JUGA:Ulasan Film Pangku Karya Reza Rahadian: Memangku Hidup yang Tak Boleh Membeku
Kehidupan yang harus dijalani Mawar terlampau pahit, bahkan bagi orang dewasa sekalipun. Kehidupan yang dia jalani terlalu berisiko karena bisa sewaktu-waktu kehilangan nyawa gara-gara siklus kekerasan yang berulang.
Namun, Mawar tidak hanya tabah, dia juga berani. Kepingan hidup Mawar selama dua tahun seperti tertulis dalam novel ini mungkin membuat pembaca tidak nyaman, getir, marah, kesal, atau bahkan ingin membalas si penindas.
Pembaca yang lain mungkin akan terus menanyakan alasan Mawar bertahan dalam kehidupan yang tidak menyenangkan itu. Bekerja di kawasan prostitusi, terjebak dalam perkawinan kontrak, dipalsukan identitasnya agar bisa menjadi pekerja seks, dan ujung-ujungnya dipenjara karena melawan penindasnya.
Mawar menunjukkan realita kota yang bagi sebagian orang (desa) dianggap sebagai solusi tekanan finansial. Faktanya, perempuan seperti Mawar yang hijrah ke kota malah menjadi korban pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan.
BACA JUGA:Resensi Novel Mawar Hitam; Antara Liku-Liku Trauma dan Ketimpangan Sosial
BACA JUGA:Resensi Haruki Murakami - Kafka on The Shore dan Kisah di Timur Jawa
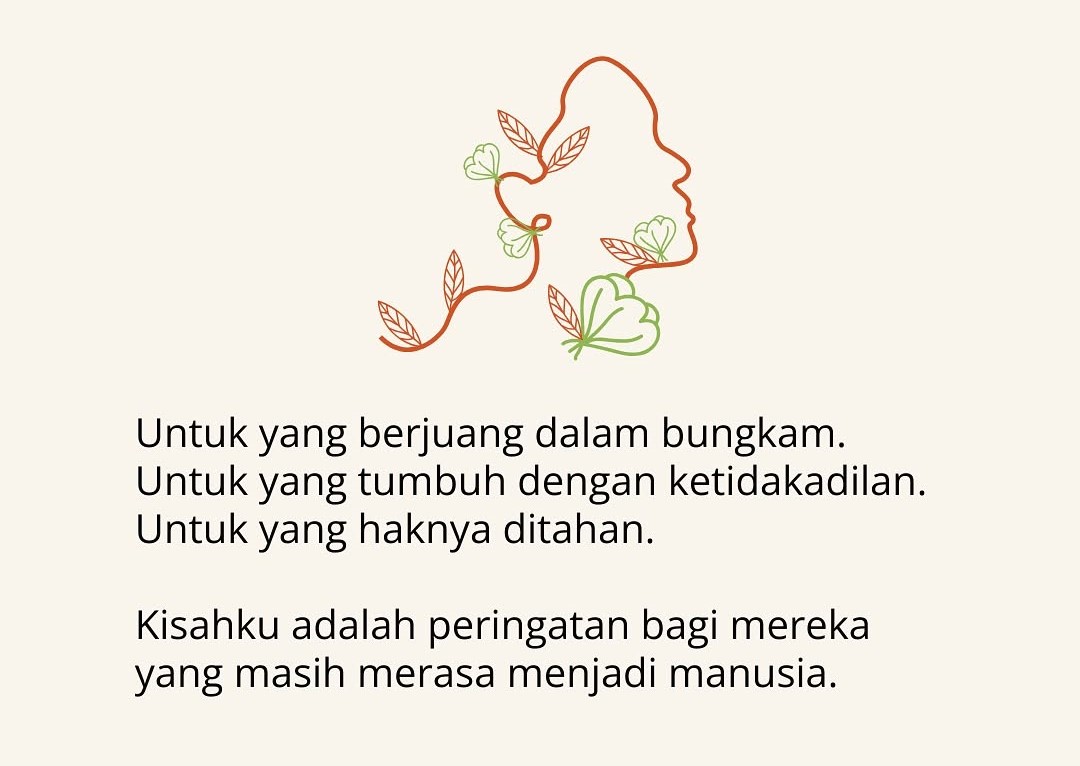
SUARA MAWAR yang digaungkan oleh para pembacanya di media sosial.--Instagram/Penerbit AkhirPekan
Dengan caranya, Mawar mengingatkan kita bahwa dunia tidak pernah diciptakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan jenis apa pun, termasuk prostitusi berkedok kawin kontrak.
Novel ini menyadarkan kita bahwa ekosistem sosial masih belum berhasil memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Khususnya, dari momok bernama perkawinan anak. Meski namanya perkawinan, pada praktiknya perkawinan anak tak lebih dari tindakan eksploitatif.
Membaca Mawar, Bukan Nama Sebenarnya menerbitkan sensasi campur aduk dalam dada. Tidak semua orang bisa menyelesaikan novel tersebut dalam sekali duduk. Ada banyak jeda yang harus dibuat agar pembaca tidak terlalu larut dalam kisah Mawar.
Dian Purnomo tidak hanya berhasil menyatukan setiap pengalaman hidup Mawar dengan komposisi bahasa yang mudah dipahami, tetapi juga mampu menyadarkan kembali pentingnya peran orang dewasa sebagai pelindung. Merekalah seharusnya yang ikut memerangi setiap bentuk eksploitasi berkedok perkawinan anak, bukan melanggengkannya.
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Kampanyekan Stop Perkawinan Anak di CFD Taman Bungkul
BACA JUGA:Angka Perkawinan Anak di Surabaya Menurun Tajam pada Semester Pertama 2024
Baik di kota maupun di desa, dampak perkawinan anak sama pedihnya. Itu adalah bukti gagalnya sistem dan budaya sebagai sarana yang membuat manusia lebih beradab. Kita, orang dewasa, tidak bisa absen dari upaya pemenuhan hak-hak anak.
Ada pengingat penting yang Dian Purnomo sematkan dalam bukunya, “TIDAK PERNAH TAMAT”. Pernyataan di halaman terakhir novelnya itu adalah pengingat bahwa ada banyak Mawar --penyintas kekerasan, penyintas kejahatan seksual, penyintas piciknya pola pikir orang dewasa-- yang masih akan bermunculan selama patriarki dilanggengkan. (*)
*) Penulis adalah staf Savy Amira Women's Crisis Center
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: