Merespons Kebangkitan Tiongkok
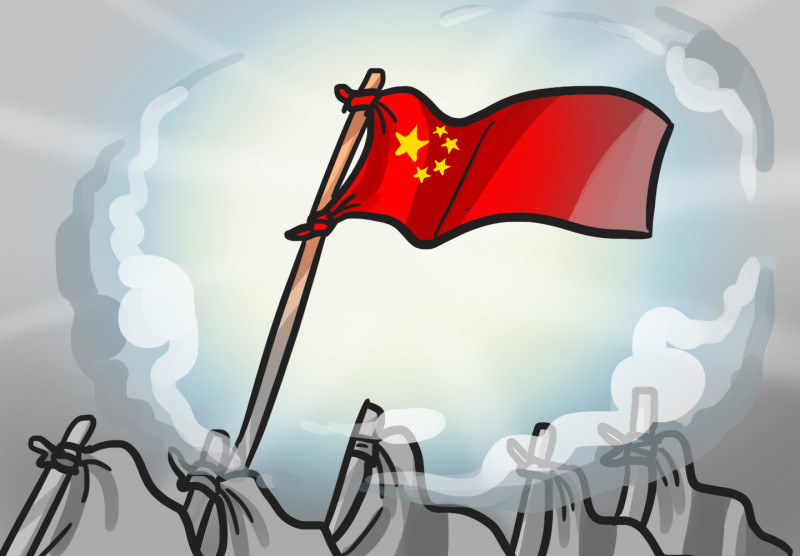
Harian Disway - TAK ADA yang mengira Tiongkok bisa sedigdaya saat ini. Ketika pada awal 80-an kebijakan reformasi dan keterbukaan diberlakukan, yang dipikirkan pemimpin Tiongkok kala itu simpel belaka: bagaimana agar rakyat Tiongkok bisa makan, tidak lagi menderita kelaparan akut yang memakan korban jiwa tak terperikan laiknya tahun-tahun sebelumnya. Tanpa dinyana, ekonomi Tiongkok meroket. Masyarakat dan negaranya sama-sama kaya raya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Banyak kalangan –termasuk pemangku kebijakan di Barat– meyakini, seiring makin makmurnya Tiongkok, negara itu akan menjadi ”Barat” juga pada akhirnya. Dalam arti, sistem politiknya akan mengimani demokrasi; sistem ekonominya akan menganut liberalisme.
Tatkala Tiongkok pada 2001 masuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), misalnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton sesumbar. ”Dengan bergabung dengan WTO, Tiongkok tidak hanya setuju untuk mengimpor lebih banyak produk kita, tetapi juga setuju untuk mengimpor salah satu nilai demokrasi yang paling dihargai: kebebasan ekonomi. Ketika individu memiliki kekuatan... untuk mewujudkan mimpi mereka, mereka akan menuntut suara yang lebih besar.”
Karena itulah, negara-negara demokratis yang 12 tahun sebelumnya mengembargo Tiongkok lantaran Peristiwa Tiananmen 1989 mau menerima Tiongkok sebagai anggota WTO. Mereka hakulyakin, dengan merangkul Tiongkok, akan bisa mengubah negara ini dari dalam.
Namun, keyakinan bisa ”mem-Barat-kan” Tiongkok tersebut hingga kini tampaknya masih jauh panggang dari api. Lebih ironisnya lagi, di Barat sendiri sekarang mulai ada kecemasan Tiongkok akan membalikkan keadaan: bisa-bisa justru Barat yang ”di-Tiongkok-kan” –atau lebih gamblangnya: ”di-komunis-kan”. Mantan Menlu AS Mike Pompeo blak-blakan mengingatkan (23/7/2020), "If the free world doesn't change Communist China, Communist China will change us."
Kekhawatiran Barat itu barangkali masuk akal. Soalnya, selain sistem ekonomi dan politik Tiongkok yang belum ada tanda-tanda akan ”ter-Barat-kan”, militer Tiongkok malah kian perkasa seiring dengan terus meningkatnya anggarannya. Dihitung dengan inflasi pun, besaran anggaran militer Tiongkok tetap mampu membuat banyak negara ketar-ketir.
Bayangkan, dari 1997 sampai 2020, anggaran militer Tiongkok telah naik paling tidak 600 persen, seperti diperinci Richard A. Bitzinger dan James Char dalam tulisannya yang dimuat National Interest (17/10/2021). Untuk tahun 2021 ini saja, masih lebih besar anggaran militer Tiongkok ketimbang APBN Indonesia.
Kendati pemerintah Tiongkok menegaskan peningkatan anggaran militer negaranya adalah untuk ”fangyu xing” (pertahanan), bukan untuk ”jingong xing” (penyerangan), tetap saja banyak negara yang menaruh curiga. Maklum, dalam teori hubungan internasional, khususnya mazhab realisme, suatu negara memang didorong untuk suuzan kepada negara lain karena tak ada yang bisa memastikan apa tujuan sebenarnya negara itu. Intinya, kebijakan yang diambil terkait negara lain harus didasarkan pada premis bahwa negara tersebut adalah ancaman bagi eksistensi negara sendiri.
Makanya, mungkin bisa dimengerti jika belakangan banyak pihak yang khawatir Tiongkok dan Amerika Serikat akan terjerembap pada apa yang oleh Graham Allison sebut sebagai ”Thucydides trap”. Jebakan yang dinamai berdasar nama sejarawan agung penulis mahakarya History of the Peloponnesian War itu, Allison gunakan untuk mengistilahkan tak terelakkannya perang antara negara mapan (established power) versus negara yang tengah bangkit (rising power).
Penyulut perang macam itu adalah takutnya negara mapan tergantikan posisinya oleh negara yang tengah bangkit –persis Perang Peloponnesia yang dikobarkan Sparta (established power) terhadap Athena (rising power) dari 431 hingga 404 SM.
Dalam buku Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (2017), Allison mencatat, dari 16 kali persaingan pergantian kekuasaan (power shift) antara established power dengan rising power yang terjadi selama 500 tahun terakhir, 12 di antaranya (75 persen) berakhir dengan peperangan.
Berangkat dari fenomena historis itu, Allison menengarai probabilitas terjadinya perang antara Amerika Serikat lawan Tiongkok di kemudian hari adalah tinggi sekali. Sebab, seperti beberapa tahun sebelumnya dinyatakan John Mearsheimer dalam The Tragedy of Great Power Politics (2001), sama dengan negara mana pun di dunia, Tiongkok tidak akan bisa bangkit secara damai.
Walakin, dalam orasi ilmiahnya di Harvard University (15/10/2018), Zhang Weiwei, akademisi Tiongkok yang pernah menjadi penerjemah Deng Xiaoping, meragukan kemungkinan terperosoknya Tiongkok ke dalam ”jebakan Thucydides”. Baginya, sejak dahulu kala, Tiongkok tidak mempunyai gen mengekspansi negara lain –bahkan ketika kekuatan Tiongkok jauh lebih besar ketimbang Barat seperti zaman Cheng Ho sekalipun. Terlebih, dari 12 contoh kasus negara-negara yang terjerat ”jebakan Thucydides” tadi, kata Zhang, semuanya adalah negara Barat, tak ada satu pun yang melibatkan Tiongkok.
Kalau begitu, lantas bagaimana kita mesti menyikapi kebangkitan Tiongkok? Konsep ”tawassuth” (moderat), ”tawazun” (seimbang), ”i’tidal” (lurus), dan ”tasamuh” (toleran) dalam Islam barangkali layak dipakai. Pasalnya, melulu melihat Tiongkok sebagai ancaman bisa jadi akan membuat kita ketinggalan peluang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:







