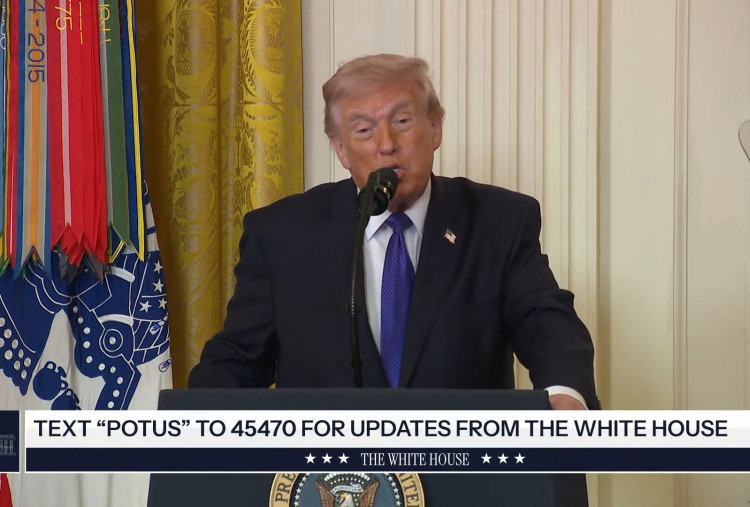Yang Tak Kunjung Padam: Kisah Para Eksil yang Disingkirkan Bangsa Sendiri

Soe Tjen Marching menunjukkan bukunya yang didiskusikan di markas KontraS Surabaya, Sabtu, 1 April 2023.-Erni Prasetyo-Harian Disway-
Soe Tjen Marching, penulis yang membukukan banyak kisah tentang peristiwa 1965, merilis buku terbarunya: Yang tak Kunjung Padam. Berbeda dengan kebanyakan bukunya yang mengungkap para korban di Indonesia, buku itu justru berkisah tentang eksil di luar negeri.
EKSIL adalah mereka yang diasingkan dan tidak bisa kembali ke Indonesia karena berbagai alasan terkait peristiwa tahun 1965.
Buku setebal 330 halaman ini berjudul lengkap Yang tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman. Buku tersebut dirilis dan didiskusikan di Markas KontraS Surabaya, Jalan Monginsidi 5, Sabtu, 1 April 2023.
Siang itu Soe Tjen tampil dengan gayanya yang santai. Perempuan kelahiran Surabaya pada 1971 tersebut tampak semringah sepanjang diskusi yang didampingi moderator Shafira Noor Adlina, salah satu member KontraS; serta Andy Irfan, Sekjen Federasi KontraS.
Buku yang baru dirilis itu berbeda dari sebagian besar karya Soe Tjen sebelumnya. Misalnya, Dari dalam Kubur yang rilis pada 2021 dengan kisah tentang perempuan-perempuan eks Gerwani, korban dari apa yang disebutnya sebagai Genosida 65.
Dikenal sebagai penulis kisah-kisah seputar tragedi ‘65, Soe Tjen menuturkan pertemuannya dengan salah satu eksil di Jerman pada tahun 2014. "Namanya Pak Ibrahim Isa. Beliau tanya pada saya, ’Soe Tjen, kamu sering menulis tentang korban 1965 di Indonesia. Kenapa kamu tidak menulis eksil?’," katanya.
Setelah menyampaikan itu, Soe Tjen yang tersenyum lantas menunjuk ke arah pengunjung. Seakan memastikan, bahwa persepsi tentang eksil yang ada dalam kepalanya, sama dengan persepsi mereka. "Bahwa eksil itu sebenarnya bukan korban langsung. Mereka ada di luar negeri. Awalnya susah, sekarang mungkin bisa hidup enak," ungkapnya.
Asumsi itulah yang dia utarakan pada Ibrahim ketika itu. "Pak Ibrahim tertawa. Ia bilang bahwa kehidupan eksil pun sangat sulit. Mereka disingkirkan oleh bangsa sendiri," ujar dosen senior Departemen Bahasa dan Budaya, SOAS University of London itu.
Sejak saat itu Soe Tjen tertarik untuk melakukan riset tentang eksil 1965. Para eksil itu dulu merupakan para mahasiswa yang dikirim pemerintah ke luar negeri. Namun yang diasingkan dan dianggap sebagai eksil adalah mereka yang punya hubungan dengan PKI. Juga mereka yang belajar di negara-negara Eropa Timur yang berhaluan komunis.

Layani peserta diskusi, Soe Tjen Marching meneken buku Yang Tak Kunjung Padam seusai diskusi di markas KontraS Surabaya, Sabtu, 1 April 2023.-Erni Prasetyo-Harian Disway-
Dalam proses penelitiannya, Soe Tjen bertemu dengan beberapa eksil. Salah satunya adalah Roesjdy Maruhun. Lulusan Moskow yang mendapat suaka di Belanda. Mendapatkan suaka dan menjadi warga negara Belanda ketika itu cukup mudah. Terutama bagi mereka yang lahir sebelum tahun 1947. "Karena orang-orang yang lahir sebelum tahun itu, tercatat lahir di Hindia Belanda. Jadi, menjadi warga negara Belanda itu mudah," katanya.
Roesjdy merupakan eksil yang tetap mempertahankan paspor Belandanya di Indonesia. Saat diperbolehkan kembali ke Indonesia, ia menolak menandatangani pernyataan kesetiaan kepada negara. Ia punya alasan. "Roesdy dulu dirampas paspornya, dicabut kewarganegaraannya oleh pemerintah saat itu. Maka, pemerintah wajib mengembalikan paspornya. Bukan menyuruh ia untuk tanda-tangan ini-itu," ujar alumni SMAK St. Louis, Surabaya itu.
Eksil Jerman dipilih karena selain mereka punya suara paling keras dalam menentang Orde Baru. Jumlah mereka pun cukup banyak dan menyimpan banyak kisah-kisah menarik. Sebab, Jerman menjadi negara tujuan bagi para eksil yang berada di Rusia supaya dapat berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia.
"Karena saat itu (Dekade ’65, Red) Rusia hanya mengizinkan masyarakat mendengarkan radio negara. Otomatis tidak bisa tahu siaran radio lain. Utamanya yang menceritakan tentang kejadian di Indonesia," ungkapnya.
Saat itu, Jerman dibagi menjadi dua. Yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Para eksil di Jerman Timur banyak berpindah ke Jerman Barat demi mendapatkan informasi. Karena Jerman Barat saat itu dikuasai negara-negara barat dengan orientasi politik dan penyediaan informasi yang lebih terbuka.
Dalam risetnya, Soe Tjen berkisah bahwa untuk menyeberang dari Jerman Timur ke Jerman Barat, harus melalui Zoologischer Garten, stasiun di Berlin Barat yang cenderung bebas. "Stasiun itu menjadi batas antara Jerman Timur dan Barat. Sangat terbuka dan tak ada pemeriksaan. Jadi eksil politik mudah meminta suaka di wilayah Jerman," ungkapnya.
Eksil politik di Jerman pun memiliki kegiatan yang cukup aktif dan membentuk organisasi. Mereka bahkan menerbitkan majalah bersama. Meski suara mereka tak begitu didengar oleh Orde Baru, namun cukup membuat persepsi internasional cenderung buruk pada Indonesia, utamanya tentang kejadian 1965.
Andy, Sekjen KontraS, menyebut bahwa semua tulisan tentang kejadian 1965 merupakan memori kolektif yang membawa siapa saja pada pertempuran yang tak pernah selesai. "Mungkin bisa selesai, apabila kebenaran tentang peristiwa tersebut sudah terungkap. Kejadian itu menimbulkan luka yang dalam. Semoga generasi mendatang tidak teracuni oleh kabar-kabar yang simpang siur," ungkapnya.
Para eksil tak semuanya terlibat dalam PKI. Sangat banyak dari mereka yang hanya belajar di luar negeri karena memperoleh beasiswa dari pemerintah. Tanpa tahu atau ikut campur apa pun tentang partai itu. Maka pengucilan mereka, bahkan pencabutan kewarganegaraan, adalah bentuk kesewenangan pemerintah Orde Baru.
Dalam buku Yang tak Kunjung Padam, Soe Tjen mematahkan asumsi bahwa eksil bukan "korban sungguhan" dari peristiwa 1965. Pun, dalam buku tersebut Soe Tjen mendedah terminologi eksil dan mengaitkannya dengan sikap politik pemerintah terhadap mereka yang mendapatkan label itu. (Guruh Dimas Nugraha)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: