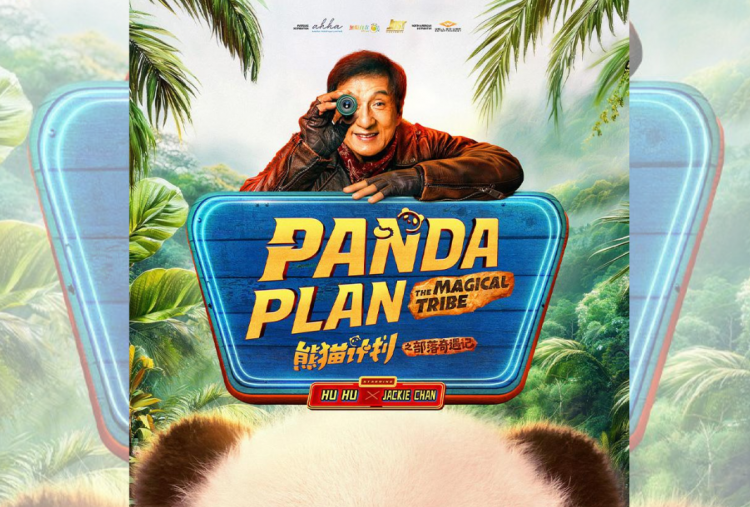Demo dan Rindu Tokoh Kultural

Sosial media.--
Kondisi hari ini jauh lebih kompleks dibanding 1998. Jika dulu suara rakyat terpusat di jalan-jalan dan halaman kampus, kini suara itu terpecah di ratusan bahkan ribuan ruang digital. Media sosial membuka ruang publik baru, tetapi sekaligus menghancurkan kesatuan percakapan. Kini kita hidup dan berada dalam network society: masyarakat jaringan yang bergerak mengikuti arus informasi dan logika algoritma.
Di dalam jaringan ini, wacana tidak lagi mengalir secara linier, melainkan meloncat-loncat mengikuti tren dan “viralitas”. Rakyat muda berdebat sengit di Twitter atau TikTok, pemerintah memilih bicara lewat televisi dan konferensi pers, sementara buzzer sibuk menciptakan narasi tandingan yang terorganisir. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya deliberatif—tempat argumen diuji secara sehat—berubah menjadi ruang algoritmik, di mana yang dominan bukan kebenaran, melainkan apa yang paling ramai diklik, dibagikan, dan diperdebatkan.
Fenomena ini melahirkan paradoks. Di satu sisi, demokrasi tampak hidup karena semua orang bisa bicara. Tetapi di sisi lain, kualitas percakapan publik menurun karena yang diperjuangkan bukan kebenaran, melainkan atensi. Dalam logika algoritma, emosi lebih cepat laku daripada argumen, sensasi lebih menarik daripada refleksi. Itulah mengapa konflik digital sering lebih panas daripada konflik nyata.

Gedung sisi barat Grahadi dibakar massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.-Moch Sahirol Layeli/Harian Disway-
Di tengah kerumunan digital yang riuh itu, tantangannya jelas: bagaimana tokoh kultural bisa hadir tanpa kehilangan otoritasnya? Bagaimana mereka menyuarakan kebijaksanaan tanpa terseret logika buzzer dan arus “like” semata? Tokoh kultural perlu membawa human touch --- kehadiran manusiawi yang menenangkan, memberi kedalaman, dan menghadirkan makna—ke dalam percakapan daring. Mereka harus sanggup menjadi jangkar moral di tengah arus yang serba cepat dan dangkal.
Beberapa tokoh sebenarnya telah mencoba. Gus Mus, misalnya, menggunakan Twitter dan Instagram bukan untuk sensasi, melainkan untuk menyebarkan kebijaksanaan. Ucapannya pendek, kadang berupa doa atau gurauan, tetapi memberi kedalaman dan menyejukkan hati. Romo Franz Magnis-Suseno tetap menulis refleksi panjang, meski tidak viral, namun memberi bobot moral yang membuat publik berpikir ulang sebelum menghakimi. Cak Nun dengan komunitas Maiyah-nya memanfaatkan ruang digital untuk mempertemukan orang-orang dalam dialog kultural, bukan sekadar debat kusir.
Mereka memberi teladan: tokoh kultural tidak harus menolak teknologi, tetapi harus hadir dengan jati diri, bukan larut dalam logika pasar digital. Kehadiran mereka di ruang maya ibarat mata air di tengah padang: menyejukkan, memberi arah, dan menjaga percakapan tetap manusiawi.
Sayangnya, tidak banyak figur semacam itu. Banyak tokoh publik lebih sibuk dengan selebrasi. Ada yang tergoda ikut arus konten viral agar tetap relevan, ada pula yang sibuk menyiapkan panggung politik untuk meraih jabatan. Padahal, publik justru rindu kesederhanaan: tokoh yang tidak mengejar sorotan kamera, melainkan rela berjalan di lorong-lorong sepi, menemui rakyat kecil, mendengarkan suara lirih yang jarang terdengar.
Tokoh kultural sejati tidak mencari panggung, melainkan menyediakan panggung bagi orang lain. Mereka tidak menambah kebisingan digital dengan sensasi baru, melainkan menyodorkan kedalaman makna. Kehadiran mereka di ruang digital seharusnya seperti tetesan embun: menenangkan, memberi arah, dan menjaga percakapan publik tetap manusiawi.
Di setiap daerah, ada kiai pesantren, romo gereja, budayawan, seniman, akademisi, atau tokoh adat yang dipercaya. Mereka dekat dengan rakyat, memahami bahasa komunitas, dan dipercaya lintas golongan. Pemerintah seharusnya memberi ruang nyata bagi mereka, bukan sekadar undangan seremonial. Mereka bisa menjadi mediator moral yang meredam konflik dan memperkuat kohesi sosial.
Demonstrasi sebagai Alarm
Demonstrasi adalah alarm. Ia menandakan ada yang salah dalam komunikasi antara rakyat dan negara. Jika alarm ini hanya dijawab dengan penangkapan, dengan deretan pasal, atau konferensi pers, maka jurang hanya akan melebar.
Yang kita butuhkan adalah jembatan manusiawi. Hari ini, kita tidak sedang kekurangan suara. Kita sedang kekurangan kepercayaan. Tokoh kultural, dengan otoritas moralnya, bisa menjadi jembatan itu. Mereka mengurangi selebrasi, mengurangi formalitas, dan menekankan kehadiran nyata.
Demonstrasi bukan musuh demokrasi. Ia justru energi korektif. Tapi ketika komunikasi politik buntu, demo bisa meledak tak terkendali. Kehadiran tokoh kultural sangat dibutuhkan, bukan untuk memadamkan, melainkan untuk menjembatani.
Jika pemerintah mau mendengar, rakyat mau berbicara dengan jujur, dan tokoh kultural hadir sebagai penengah, maka demonstrasi bisa berubah dari teriakan marah menjadi dialog sehat. (*)
*) Dosen Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: