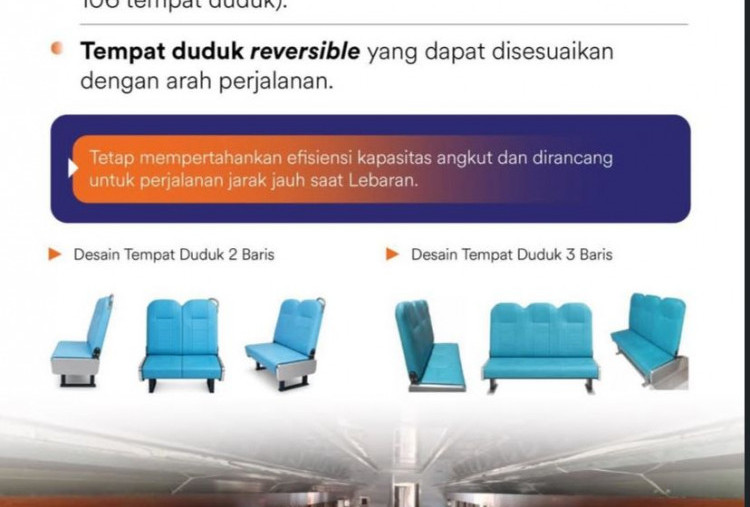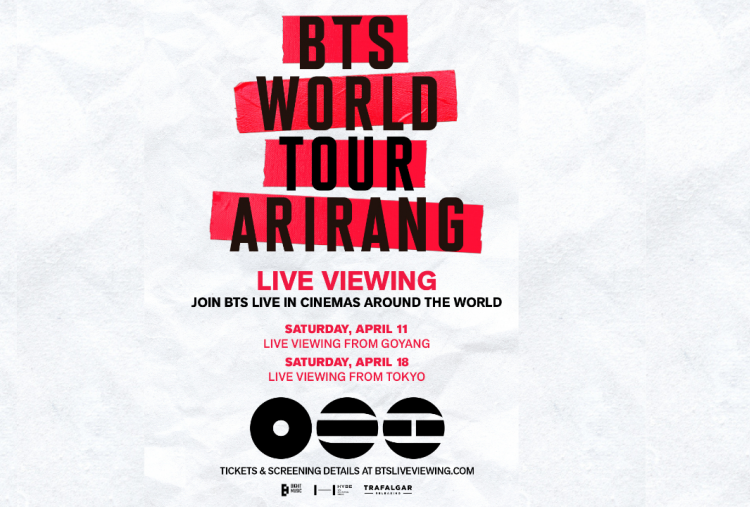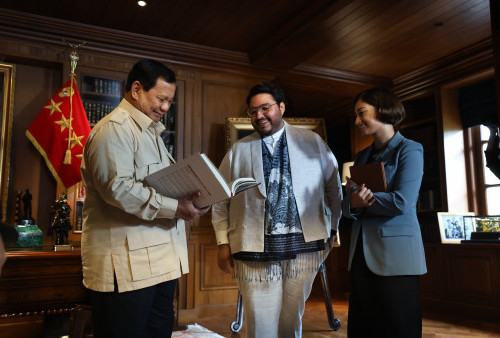Terjemahan Transisi Energi Berkeadilan Tanpa FPIC

ILUSTRASI Terjemahan Transisi Energi Berkeadilan Tanpa FPIC.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
INDONESIA merdeka sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Namun, di balik itu ada satu paradoks besar: masyarakat adat, sang penjaga tanah, hutan, dan biodiversitas, tak pernah sungguh-sungguh diperhitungkan dalam pengelolaan republik ini.
Di era transisi energi hijau, proyek-proyek PLTA, tambang nikel untuk baterai, hingga panas bumi masuk ke wilayah adat tanpa free, prior, and informed consent (FPIC).
Seolah masyarakat adat dianggap tidak ada, tidak penting, dan bukan bagian dari rakyat yang harus dihormati kedaulatannya.
BACA JUGA:PGN Angkat Direksi Baru, Siapkan Strategi Besar di Tengah Transisi Energi
BACA JUGA:Festival Energi Mineral 2025: Upaya ESDM Gaet Generasi Muda dan Perkuat Transisi Energi
Pertanyaannya, apa sebenarnya akar masalah sehingga negara ini terus-menerus mengabaikan sebagian rakyatnya yang justru hidup paling dekat dengan alam?
Memang benar, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sudah memberikan pengakuan atas masyarakat hukum adat. Namun, ada syarat yang membuat pengakuan itu setengah hati: ”sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”.
Kalimat itu menempatkan kepentingan masyarakat adat tersubordinasi dan eksistensi mereka berada di bawah kendali negara.
BACA JUGA:Pertamina Dorong Inovasi Mahasiswa Lewat PGTC 2025, Fokus pada Transisi Energi Berkelanjutan
Pada masa Belanda, masyarakat adat sudah ada. Mereka punya living law, sistem pemerintahan lokal, hukum adat, wilayah ulayat, dan kosmologi tersendiri. Di masa itu, ada pengakuan parsial: Adatrecht sebagaimana diteliti oleh Cornelis van Vollenhoven.
Namun, pengakuan itu bersifat administratif untuk kepentingan kolonial, seperti mengatur tanah adat dalam kerangka Domeinverklaring yang menyatakan tanah tanpa sertifikat dianggap milik pemerintah kolonial.
Jadi, sejak dulu sudah ada kontradiksi: hukum adat diakui, tetapi kedaulatan adat ditekan. Setelah merdeka, pola itu diteruskan. Negara melihat tanah adat bukan sebagai ruang hidup, tetapi sebagai aset pembangunan.
BACA JUGA:Dukung Kemandirian dan Transisi Energi Bersih, Pertamina Sepakati 10 Perjanjian Jual Beli Gas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: