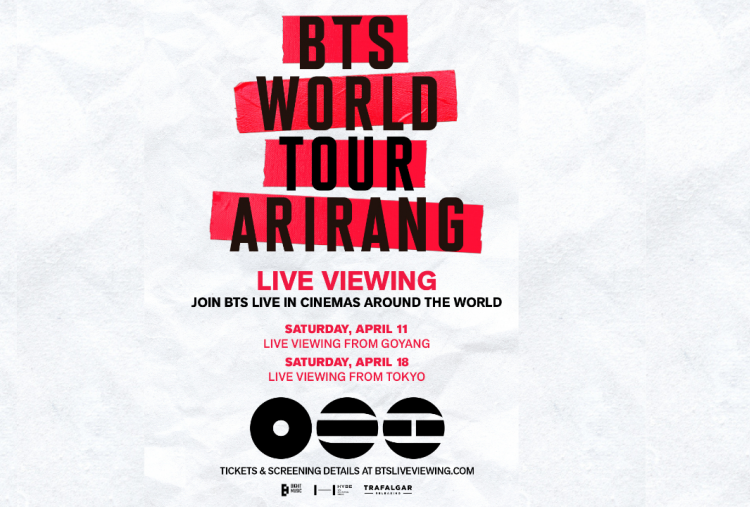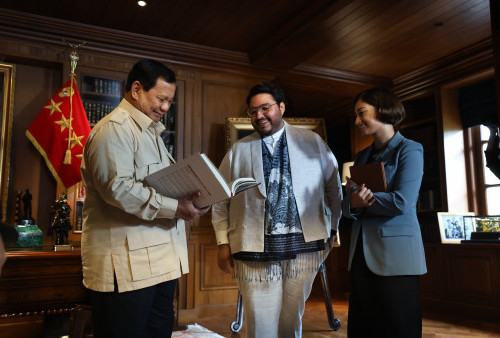Terjemahan Transisi Energi Berkeadilan Tanpa FPIC

ILUSTRASI Terjemahan Transisi Energi Berkeadilan Tanpa FPIC.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
BACA JUGA:Indonesia Punya Cadangan Biofuel Melimpah, Bisa Jadi Kunci Transisi Energi Terbarukan
Puncak marginalisasi terjadi di era Orde Baru. Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menempatkan seluruh hutan di bawah status ”hutan negara”.
Hutan adat lenyap dari peta hukum nasional. Dengan legitimasi itu, jutaan hektare hutan dibuka untuk logging, perkebunan sawit, pertambangan, hingga proyek transmigrasi.
Masyarakat adat yang menolak disebut sebagai ”penghambat pembangunan”. Konflik agraria, penggusuran, bahkan kriminalisasi menjadi kenyataan sehari-hari.
BACA JUGA:Percepat Transisi Energi, Perusahaan Green Energy Didorong untuk IPO
BACA JUGA:PLN Jatim Jalin Kerjasama dengan Untag Surabaya Percepat Transisi Energi Menuju NZE 2060
Reformasi 1998 memberikan harapan baru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara. Itu tonggak penting pembuka ruang pengakuan lebih luas bagi masyarakat adat.
Namun, putusan itu hanya berlaku sebagai tafsir hukum. Tanpa payung hukum yang kuat, pengakuan tersebut akan berhenti di tataran wacana.
Karena itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi krusial sebagai instrumen legislasi yang bisa mengikat negara. Sayangnya, hingga kini RUU itu tak kunjung disahkan. Akibatnya, masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan.
Sementara itu, prinsip FPIC yang diakui secara internasional melalui UNDRIP 2007 dan ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples (1989) belum bisa dijadikan pijakan kuat di Indonesia.
FPIC adalah hak dasar masyarakat adat untuk memberi atau menolak persetujuan atas proyek yang memengaruhi hidup mereka. Indonesia belum meratifikasi ILO 169 of 1989 sehingga FPIC tidak mengikat.
Artinya, tidak ada kewajiban hukum bagi Indonesia untuk terlebih dahulu mendapatkan FPIC dari masyarakat adat sebelum menjalankan proyek-proyek energinya di wilayah adat.
Akibatnya, di era transisi energi, pembangunan PLTA Batang Toru di Sumatera Utara justru mengancam hutan adat dan habitat orang utan Tapanuli. Tambang nikel di Sulawesi menyingkirkan komunitas adat dari tanahnya demi baterai kendaraan listrik.
Proyek panas bumi di berbagai daerah berpotensi memicu konflik serupa. Ketika dunia berteriak ”energi hijau”, justru di Indonesia masyarakat adatnya mengalami ”penggusuran hijau”. Ironis.
Mengapa itu bisa terjadi? Sebab, sejak awal, kontrak sosial dengan masyarakat adat tidak pernah ada. Negara lahir dengan visi homogenisasi, membayangkan ”bangsa Indonesia” sebagai kesatuan tunggal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: