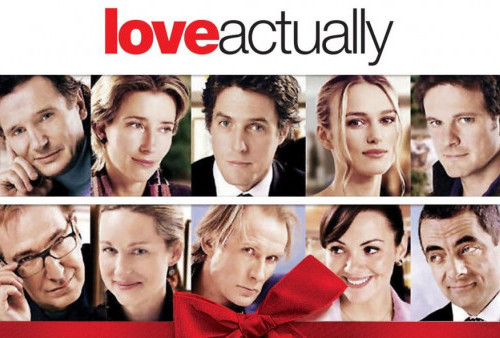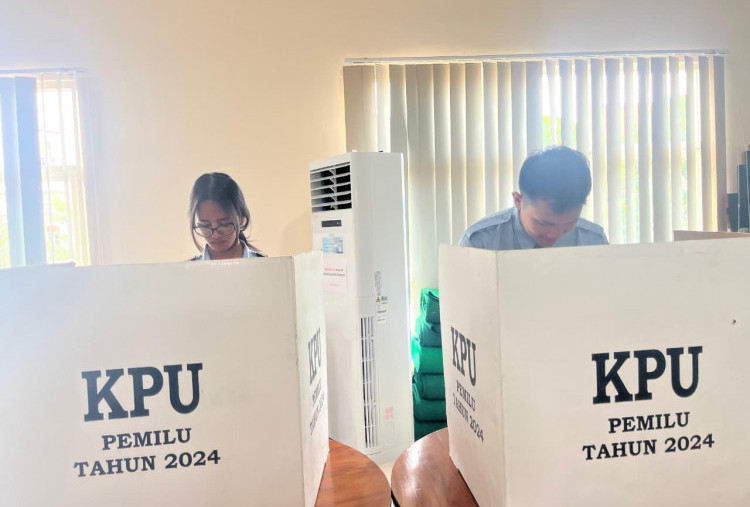Berhala di Era Digital

Ilustrasi Berhala di Era Digital.-Pexels-Pexels
Hal serupa terlihat dari insiden wakil bupati Padang Pariaman yang diusir warganya. Bukannya menunggu penjelasan atau proses dialog, kemarahan yang dipicu oleh narasi digital yang cepat menyebar langsung menggerakkan massa untuk menyampaikan ketidakpuasan secara langsung.
Kenyataan itu memperlihatkan bahwa ruang digital, bukannya menjadi medium pencerahan, justru menjadi pemicu kegaduhan yang rentan menggeser fokus dari substansi.
Kebijakan yang rumit sering kali disederhanakan menjadi meme atau viral di media sosial. Lalu, reaksi emosional publik menjadi barometer utama bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan.
Fenomena itu berdampak nyata hingga ke ranah politik tertinggi. Keputusan strategis, seperti wacana reshuffle kabinet, seolah-olah hanya didasari oleh kegaduhan di media sosial. Hal itu menunjukkan para pengambil keputusan pun rentan terdistraksi oleh riuh rendah di dunia maya.
Apakah reshuffle dilakukan murni berdasar evaluasi kinerja yang mendalam ataukah juga dipengaruhi desakan publik yang tercipta dari sentimen digital yang cepat berubah? Jika politisi hanya berfokus pada apa yang ”paling viral”, mereka akan gagal melihat akar masalah yang sebenarnya dan hanya akan menjadi boneka dari berhala digital.
Itu adalah contoh dari ”politik pasca kebenaran” (post-truth politics), di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh jika dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi.
BACA JUGA:Konteks Baru Kata 'Menyala' di Era Digital
BACA JUGA:Cegah Pembunuhan Karakter di Era Digital
AGENDA KE DEPAN
Fenomena di atas memang mengkhawatirkan, tetapi tidak berarti kita harus lari dari era digital. Jalan keluarnya adalah berproses. Kita harus beralih dari sekadar sebagai konsumen yang reaktif menjadi kreator yang proaktif dan produktif.
Berkreasi melalui konten digital bukan hanya tentang membuat video yang viral atau mencari popularitas semata, melainkan juga tentang membangun narasi yang konstruktif dan memberikan nilai edukasi.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sebuah agenda yang berfokus pada penguatan literasi digital yang kritis. Hal itu melampaui kemampuan teknis, tetapi mencakup kemampuan untuk memahami dan menantang cara kerja algoritma.
Seperti yang ditulis oleh ahli media Neil Postman dalam karyanya, Amusing Ourselves to Death, ia berargumen bahwa media baru bukan sekadar alat, melainkan sebuah ”ekosistem yang membentuk cara kita berpikir”.
Maka, tantangan kita, apakah ekosistem yang kita bangun saat ini akan mengarahkan kita pada percakapan yang substansial atau hanya pada hiburan yang dangkal?
Lebih jauh, kita harus membangun ekosistem digital yang beretika, di mana akuntabilitas publik dipulihkan. Itu dimulai dari diri sendiri, dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bias, serta dari para pengambil keputusan yang harus kembali pada evaluasi kinerja yang mendalam, bukan sekadar riuh rendah di media sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: