Albert Camus dan Absurdisme: Menertawakan Hidup yang Tak Masuk Akal

Potret Albert Camus saat muda, di masa awal karier jurnalistiknya. --wallpaperacsess
HARIAN DISWAY – Apa yang Anda lakukan saat sadar bahwa hidup ini tak punya makna? Bahwa semua usaha, cinta, dan pencapaian kita pada akhirnya akan hilang ditelan waktu, dan semesta tak peduli sedikit pun? Menyerah? Marah?
Atau, seperti yang disarankan Albert Camus, terus hidup dengan kepala tegak, menerima absurditas itu sebagai sahabat? Itulah inti dari absurdisme—sebuah pandangan filsafat yang tidak mengajak kita untuk menghindar dari kenyataan pahit kehidupan.
Tetapi justru mengajak kita menghadapinya dengan mata terbuka. Dan nama yang paling identik dengan aliran ini adalah Albert Camus. Camus adalah penulis, filsuf, dan jurnalis asal Perancis-Aljazair yang membuat dunia berpikir ulang tentang makna hidup.
BACA JUGA: Wisata di Dusun Semilir Bagai Cerita Meursault dalam Novel The Outsiders Karya Albert Camus
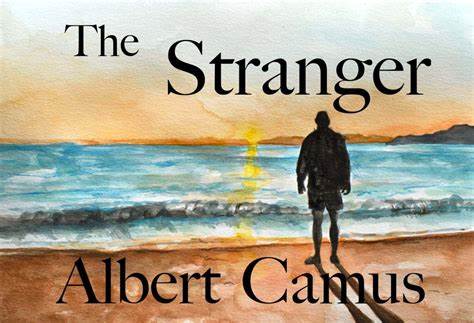
Sampul buku The Stranger yang menjadi ikon absurdisme modern. --analysisbook
Dia tidak menawarkan solusi spiritual atau dogma baru. Tetapi mengajukan pertanyaan keras: Kalau hidup ini absurd, mengapa kita hidup? Jawabannya mengejutkan: karena justru dari kesadaran akan absurditas itulah kita bisa meraih kebebasan sejati.
Filsafat Camus lahir dari pengalaman konkret: perang dunia, kolonialisme, kematian, kehilangan iman. Ia bukan filsuf menara gading. Ia adalah pemikir jalanan. Pemikir yang melihat kehidupan sehari-hari sebagai ladang refleksi paling jujur.
Absurdisme bukan aliran sesat. Ia bukan pula ajaran untuk hidup seenaknya. Ini adalah cabang pemikiran filsafat yang lahir dari pergulatan antara keinginan manusia untuk menemukan makna hidup, dan kenyataan bahwa semesta tetap bungkam.
BACA JUGA: Ngopi Bukan Sekadar Tren Berjalan, Simak Filosofi di Baliknya
Tidak ada petunjuk, tidak ada manual hidup, tidak ada skenario Tuhan yang pasti. Dalam The Myth of Sisyphus, buku esai yang menjadi fondasi absurdisme modern, Camus menjelaskan bahwa absurditas terjadi ketika dua hal bertemu.
Yakno manusia yang ingin memahami segalanya, dan dunia yang tak bisa dijelaskan. Maka lahirlah kekosongan. Sebuah jurang logika. Namun menurut Camus, dari jurang itu lahir kejujuran. Dan dari kejujuran, lahir pilihan.
Apa pilihannya? Ada tiga, menurut Camus. Pertama, bunuh diri. Tapi ini adalah pengakuan kekalahan terhadap absurditas. Kedua, lari ke agama atau sistem kepercayaan yang menjanjikan makna setelah mati.
BACA JUGA: Wong Liyo Ngerti Opo: Filosofi Stoikisme ala Daniel Spid yang Mengguncang TikTok
Tapi ini, kata Camus, adalah bentuk bunuh diri filosofis. Kita menolak realitas demi fiksi. Pilihan ketiga? Hidup berdamai dengan absurditas itu sendiri. Menyadari bahwa hidup tidak punya makna, tapi justru karena itulah kita bebas menciptakan makna kita sendiri.
Seperti Sisyphus, tokoh dalam mitologi Yunani yang dihukum mendorong batu ke atas bukit selamanya. Tugasnya sia-sia, tapi ia terus melakukannya. Dan Camus berkata: Kita harus membayangkan bahwa Sisyphus bahagia.
Albert Camus lahir di Mondovi, Aljazair (saat masih koloni Perancis), tahun 1913. Latar belakangnya bukan akademisi elite, tapi dari keluarga miskin. Ayahnya tewas di Perang Dunia I, dan ibunya bekerja sebagai pembersih rumah.
BACA JUGA: Filosofi Teras Jadi Revolusi Pemikiran Anak Muda Melalui Gagasan Stoik
Camus tumbuh dengan kepekaan sosial tinggi, sekaligus kesadaran akan ketimpangan dunia. Ia kuliah filsafat di Universitas Aljazair, tapi lebih tertarik pada teater, sastra, dan politik.
Ia sempat bergabung dalam Partai Komunis Perancis, tapi kemudian keluar karena tidak tahan dengan dogma yang kaku. Camus lebih suka berpikir bebas—tanpa embel-embel ideologi.
Saat Perang Dunia II pecah, Camus aktif dalam gerakan perlawanan terhadap Nazi. Ia menjadi editor untuk Combat, surat kabar bawah tanah yang memuat tulisan-tulisan tajam tentang moralitas, politik, dan kemanusiaan.
BACA JUGA: Setiap Kain Berfilosofi
Tulisannya tidak bertele-tele. Karya-karyanya seperti The Stranger (L’Étranger), The Plague (La Peste), dan The Fall penuh dengan atmosfer absurd, tetapi juga manusiawi.
Ia menulis bukan untuk pamer kebijakan, tapi untuk menyampaikan keresahan—dengan jujur, dan kadang brutal. Camus adalah figur langka dalam dunia filsafat: ia anti-nihilisme tapi juga anti-utopia.
Ia menolak gagasan bahwa hidup tidak berarti apa-apa, tapi juga tidak percaya bahwa ada sistem sempurna yang bisa menyelamatkan semua manusia. Baginya, hidup adalah perjuangan terus-menerus, antara absurditas dan martabat.
BACA JUGA: 5 Rekomendasi Buku Motivasi yang Bisa Mengubah Cara Pandang Hidup
Dalam The Plague, ia menciptakan tokoh dokter Rieux yang melawan wabah bukan karena yakin akan kemenangan, tetapi karena merasa itu hal yang benar. Dalam The Stranger, tokoh Meursault dihukum mati bukan karena membunuh.
Tapi karena dunia tidak tahu harus bagaimana menghadapi orang yang tak ikut drama sosial. Camus sendiri meninggal muda, dalam kecelakaan mobil tahun 1960 di usia 46.
Tapi warisannya abadi. Ia adalah suara yang mengingatkan bahwa hidup ini memang aneh, sulit, dan kadang tak adil. Tapi justru karena itu, ia layak dijalani dengan sepenuh hati.
Albert Camus mengajarkan kita bahwa menerima absurditas bukan berarti menyerah. Justru itu adalah bentuk perlawanan tertinggi terhadap dunia yang acuh tak acuh. Ia mengajak kita untuk menjadi manusia sepenuhnya—tidak tunduk pada harapan palsu, tapi juga tidak mati rasa.
BACA JUGA: Apa Itu Stoikisme? Mari Pahami dari Buku Filosofi Teras Karya Henry Manampiring
BACA JUGA: Buku 22 Ways to Self-Love yang Ditulis Reffi Dhinar Ini Bantu Perempuan Usir Minder
Absurdisme bukan tentang putus asa. Ia tentang keberanian untuk tetap hidup, bekerja, mencinta, dan bermimpi—meskipun tahu semua itu tidak punya arti abadi.
Dan yang seperti Camus katakan: Tidak ada nasib yang tidak bisa diatasi dengan penghinaan. Kita bisa menang atas absurditas, bukan dengan mengalahkannya, tapi dengan menertawakannya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:










