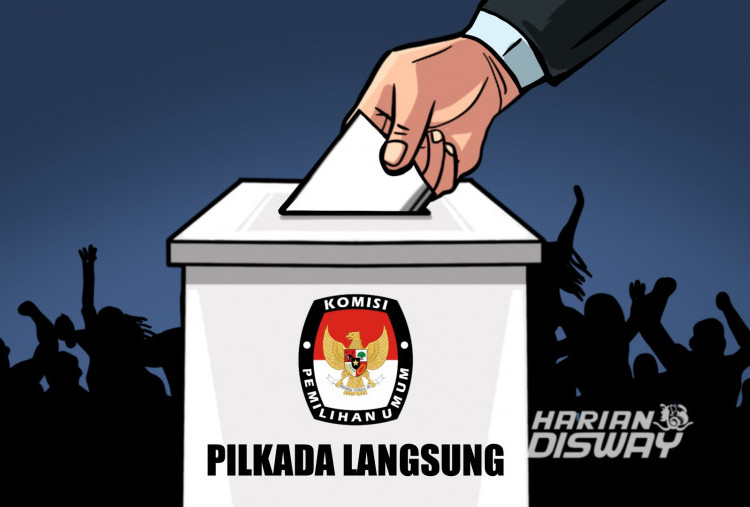Menggugah Esensi Kemerdekaan Tanah Adat

ILUSTRASI Menggugah Esensi Kemerdekaan Tanah Adat.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Namun, kebijakan itu masih menyisakan pertanyaan: seberapa jauh digitalisasi sertifikat dan penegasan kepemilikan itu benar-benar melindungi rakyat kecil, terutama yang tinggal di tanah adat tanpa sertifikat formal?
Digitalisasi sertifikat tanah memang dapat mengurangi tumpang tindih klaim, tetapi tidak otomatis mengatasi akar persoalan, terutama bagi masyarakat adat dan penghuni lahan yang tidak memiliki bukti formal.
Perspektif production of space Lefebvre (1991) mengingatkan bahwa ruang adalah produk sosial. Dengan demikian, hak warga tidak semata diukur dari dokumen legal, tetapi juga dari hubungan historis, kultural, dan ekonomi mereka dengan tanah tersebut.
Dalam kerangka itu, sertifikasi digital justru berpotensi mengukuhkan dominasi pemodal jika tidak dibarengi perlindungan substantif terhadap hak-hak nonformal.
Ketidaksesuaian peta wilayah adat dengan peta resmi negara membuka peluang tumpang tindih klaim, terutama dengan hak guna usaha (HGU) perusahaan besar (Mongabay, 2020).
Maka, pengakuan formal masyarakat adat melalui peraturan daerah menjadi langkah awal yang tidak bisa diabaikan. Tanpa legitimasi hukum, wilayah adat akan tetap ”tidak terlihat” dalam sistem BPN sehingga rentan diambil alih pihak berkekuatan modal.
Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat seharusnya diakui sebagai milik masyarakat adat, bukan lagi sebagai hutan negara (AMAN, 2013). Tanpa implementasi di tingkat daerah, putusan itu akan tinggal sebagai teks hukum tanpa daya.
Lalu, integrasi peta partisipatif ke dalam one map policy menjadi kunci pencegahan konflik. Organisasi seperti Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah memproduksi peta wilayah adat berbasis kesepakatan komunitas.
Namun, selama peta itu tidak diakui negara, tumpang tindih dengan konsesi HGU akan terus terjadi (BRWA, 2022). Di lain sisi, program GEMAPATAS perlu direvisi agar memiliki protokol verifikasi sosial-budaya sebelum pemasangan patok batas.
Langkah itu penting untuk menghindari legalisasi penguasaan tanah adat oleh pihak yang memiliki kekuatan administratif, tetapi tidak memiliki legitimasi sosial. Model itu sejalan dengan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) yang diakui secara internasional sebagai mekanisme perlindungan masyarakat adat (FAO, 2016).
Artinya, program GEMAPATAS dan sertifikasi tanah harus memastikan redistribusi manfaat, bukan sekadar administrasi kepemilikan.
Masyarakat yang kehilangan tanah akibat PSN semestinya mendapatkan lahan pengganti yang setara produktivitasnya serta kompensasi berbasis opportunity cost, bukan hanya harga pasar.
Sedangkan untuk tanah adat yang sudah masuk HGU dan sulit dikembalikan, kompensasi harus berbentuk lahan pengganti setara, bukan sekadar ganti rugi uang. Lahan pengganti itu harus dilengkapi sertifikat kolektif digital atas nama komunitas adat agar tidak kembali terfragmentasi.
Oleh karena itu, kemerdekaan sejati atas tanah tidak cukup dijamin oleh sertifikat digital. Ia harus diperkuat melalui partisipasi publik yang substantif, perlindungan hak masyarakat adat, dan penegakan prinsip keadilan ekologis.
Pembangunan nasional seharusnya memandang tanah bukan hanya sebagai komoditas, melainkan juga sebagai ruang hidup yang memerlukan keberlanjutan sosial dan ekologis, di sanalah esensi kemerdekaan bagi masyarakat adat. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: