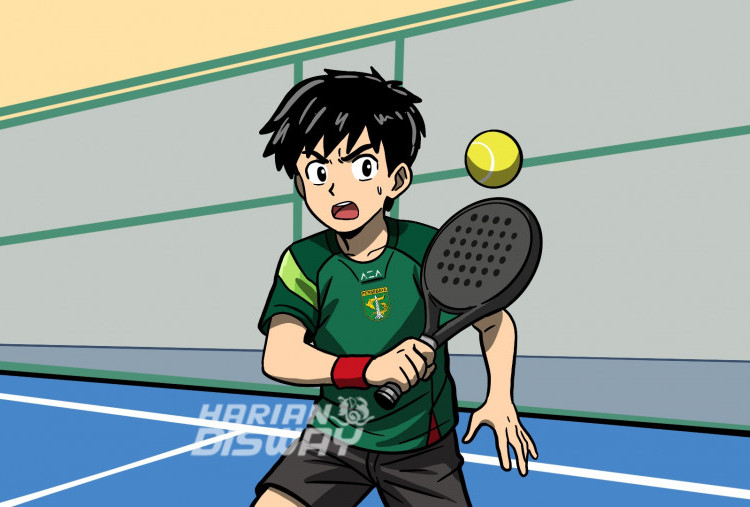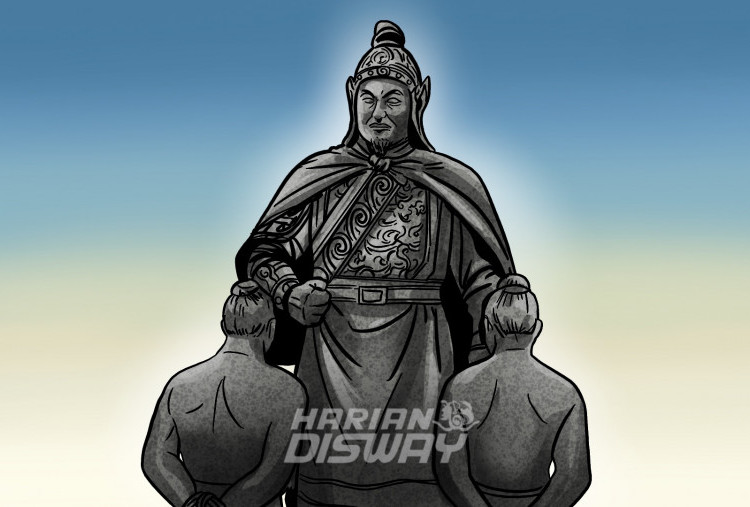Di Balik Topeng Singo Barong: Ironi Kesejahteraan Penjaga Tradisi Reog

ILUSTRASI di Balik Topeng Singo Barong: Ironi Kesejahteraan Penjaga Tradisi Reog.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi seniman, tetapi juga manajer bagi kesenian mereka sendiri.
Komunitas reog dalam hal menentukan harga pentas cenderung didasarkan pada kesediaan membayar melalui mekanisme tawar-menawar. Hal itu membuat harga pentas reog Ponorogo cenderung murah.
Fenomena tersebut menjadi indikasi bahwa literasi ekonomi pelaku seni pertujukan reog Ponorogo masih rendah. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk menyelenggarakan pendidikan ekonomi kreatif.
Itu bisa diwujudkan melalui program studi di perguruan tinggi, kurikulum kewirausahaan budaya di sekolah, hingga berbagai pelatihan informal yang mudah diakses.
Agar ekosistem kebudayaan kita sehat, para pelakunya harus berdaya secara ekonomi. Caranya bukan dengan memaksa mereka kembali kuliah, melainkan melalui pemberdayaan yang sifatnya praktis.
Penting sekali untuk mengadakan lokakarya rutin bagi para pimpinan komunitas seni, fokus pada tiga hal utama.
Pertama, perhitungan biaya produksi dan penetapan harga yang profesional. Kedua, penyusunan proposal agar bisa menembus klien korporat. Ketiga, manajemen keuangan yang transparan di dalam grup.
Selain itu, pemberdayaan itu wajib menyentuh ranah digital. Para seniman harus difasilitasi untuk go-online, entah untuk memasarkan jasa mereka lebih luas, menjual produk kerajinan, maupun membuka jalur donasi untuk regenerasi peralatan.
Membiarkan reog terus menggema di panggung dunia sementara suara rintih ekonomi para senimannya teredam adalah sebuah ironi yang tidak boleh kita biarkan berlanjut. Ini bukan lagi sekadar panggilan, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif.
Pemerintah daerah harus berhenti hanya menjadi fasilitator festival; mereka wajib menetapkan standar upah minimum yang layak bagi seniman di setiap acara yang mereka danai.
Pelaku usaha pariwisata harus mulai menciptakan paket wisata budaya di mana sebagian keuntungan dialokasikan secara adil untuk kesejahteraan seniman. Dan, kita, sebagai masyarakat, harus menjadi apresiator aktif dengan membeli cendera mata resmi atau memberikan donasi langsung, tidak hanya menjadi penonton.
Pelestarian sejati bukanlah tentang menyimpan warisan di dalam museum kaca yang dingin, lalu memolesnya hanya saat ada perayaan. Budaya yang hanya hidup di dalam etalase akan kehilangan denyutnya.
Ia mungkin akan tetap ada sebagai tontonan, tetapi jiwanya perlahan sirna. Pelestarian yang sesungguhnya adalah memastikan api semangat di dalam dada para penjaganya terus menyala terang, diwariskan dengan bangga dari generasi ke generasi, bukan sebagai beban, melainkan sebagai pilihan hidup yang terhormat.
Api semangat itu, bagaimanapun, tidak bisa menyala hanya dengan udara. Ia butuh kayu bakar. Kita tidak bisa meminta seorang seniman untuk terus berkarya dengan totalitas, sementara di saat yang sama ia cemas memikirkan nasib dapurnya.
Menghargai mahakarya reog berarti juga memuliakan para empunya. Memberikan mereka martabat ekonomi bukanlah bentuk komersialisasi yang merusak, melainkan sebuah fondasi agar mereka bisa terus berkarya dengan merdeka, tanpa dihantui oleh bayang-bayang kerentanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: