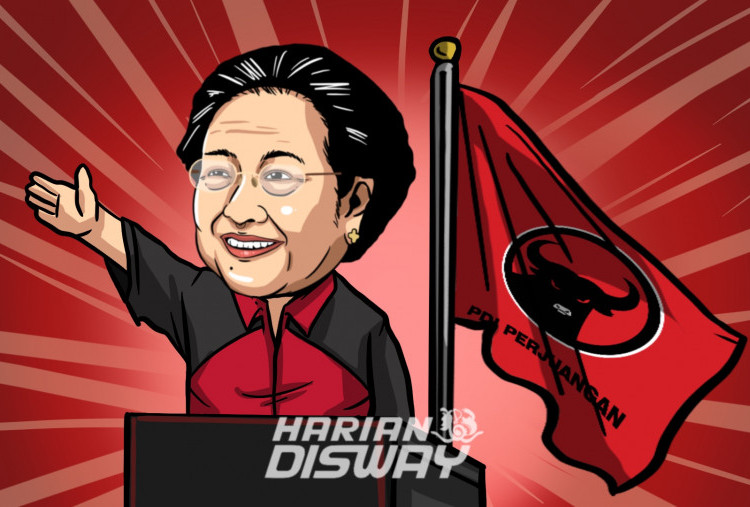Menyapu Korupsi Moral: Nurani, Ucapan Pejabat, dan Luka Rakyat

ILUSTRASI Menyapu Korupsi Moral: Nurani, Ucapan Pejabat, dan Luka Rakyat.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Fenomena serupa muncul dalam pernyataan Hasan Nasbi yang menyinggung budaya ”menjilat penguasa”.
Ucapan itu mengilustrasikan bagaimana bahasa dapat memperlihatkan sekaligus menormalisasi praktik-praktik kekuasaan yang tidak sehat. Dengan kata lain, korupsi moral kerap dimulai dari mulut, sebelum menjelma dalam tindakan nyata.
Tindakan dan penampilan pejabat publik juga tidak kalah penting. Gaya hidup mewah di tengah kesulitan rakyat adalah bentuk pengkhianatan etika. Etika publik menuntut kesederhanaan, bukan kemewahan yang dipertontonkan.
BACA JUGA:Korupsi Hakim, Subversi Negara Hukum, dan Penawaran Sistem Pidana Islam
BACA JUGA:Korupsi dan Jejaring Kekuasaan Elite
Kita tentu tidak anti kenyamanan pribadi, tetapi pejabat yang berhati nurani memilih sikap sederhana sebagai wujud empati. Ketika rakyat antre bantuan sosial, sementara pejabat publik tampil dengan kendaraan supermewah atau pesta berlebihan, yang terjadi bukan sekadar perbedaan gaya hidup, melainkan erosi kepercayaan publik.
Nurani yang hidup akan mengukur setiap tindakannya dari kacamata rakyat, bukan dari lingkaran elitenya.
Korupsi moral juga merembet ke lingkup keluarga. Fenomena nepotisme dan politik dinasti kian memperlihatkan bagaimana jabatan publik diperlakukan sebagai harta warisan, bukan amanah rakyat.
BACA JUGA:Korupsi di Pertamina, Jalan Menuju Kehancuran Negara?
BACA JUGA:Korupsi sebagai Problem Budaya
Ketika keluarga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau ketika kerabat dimajukan untuk merebut jabatan politik, rusaklah prinsip keadilan. Integritas tidak hanya diukur dari diri sendiri, tetapi juga dari kesediaan menjaga keluarga agar tidak menunggangi kekuasaan.
Korupsi finansial bisa dihitung dan diganti, tetapi korupsi moral merusak sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kepercayaan.
Sejarah filsafat politik mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak terkendali akan melahirkan tirani, sedangkan politik sejati seharusnya diabdikan bagi kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan keluarga atau golongan.
Kekuasaan yang kehilangan transparansi dan koreksi moral akan berubah menjadi mekanisme pengawasan yang menindas. Dalam situasi seperti itu, kejahatan tidak selalu tampil dengan wajah bengis; bisa lahir dari orang-orang biasa yang berhenti berpikir secara moral dan hanya mengikuti arus birokrasi.
Mereka mungkin tidak merasa ”jahat”, tetapi dengan membiarkan korupsi moral berjalan atau mendiamkan praktik nepotisme, mereka justru berkontribusi pada kerusakan bangsa secara banal –seolah-olah hal itu rutinitas yang normal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: