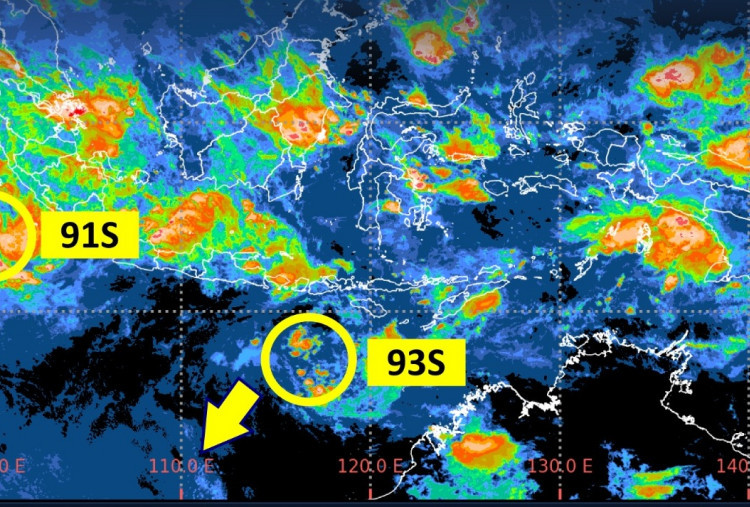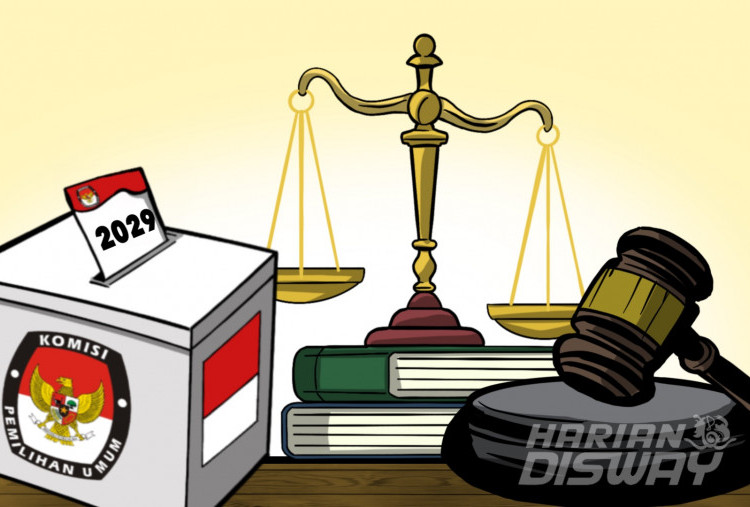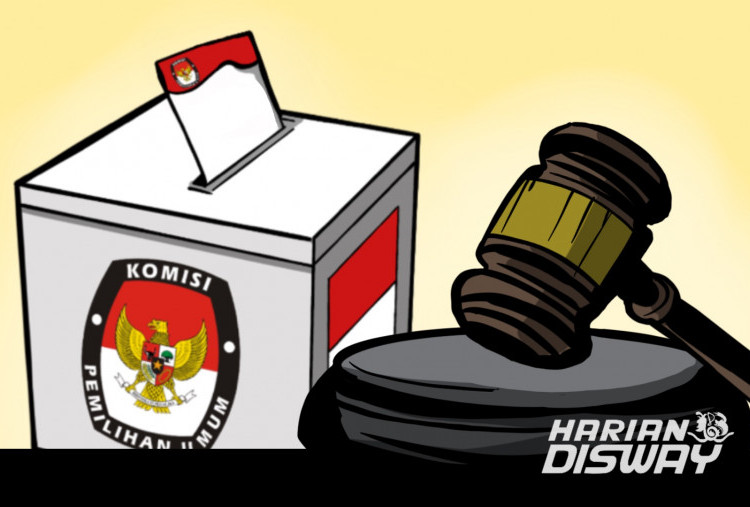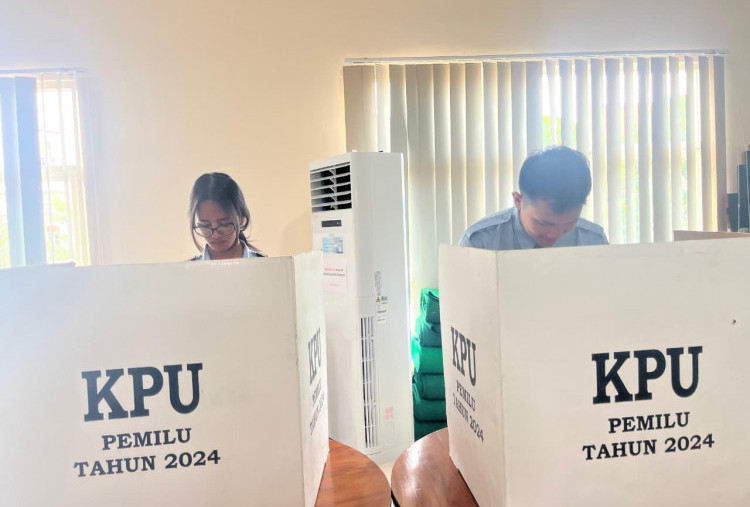Menjaga Kewarasan Publik: Mengawal Transisi 2029 dari Jebakan ”Ritual” Hukum
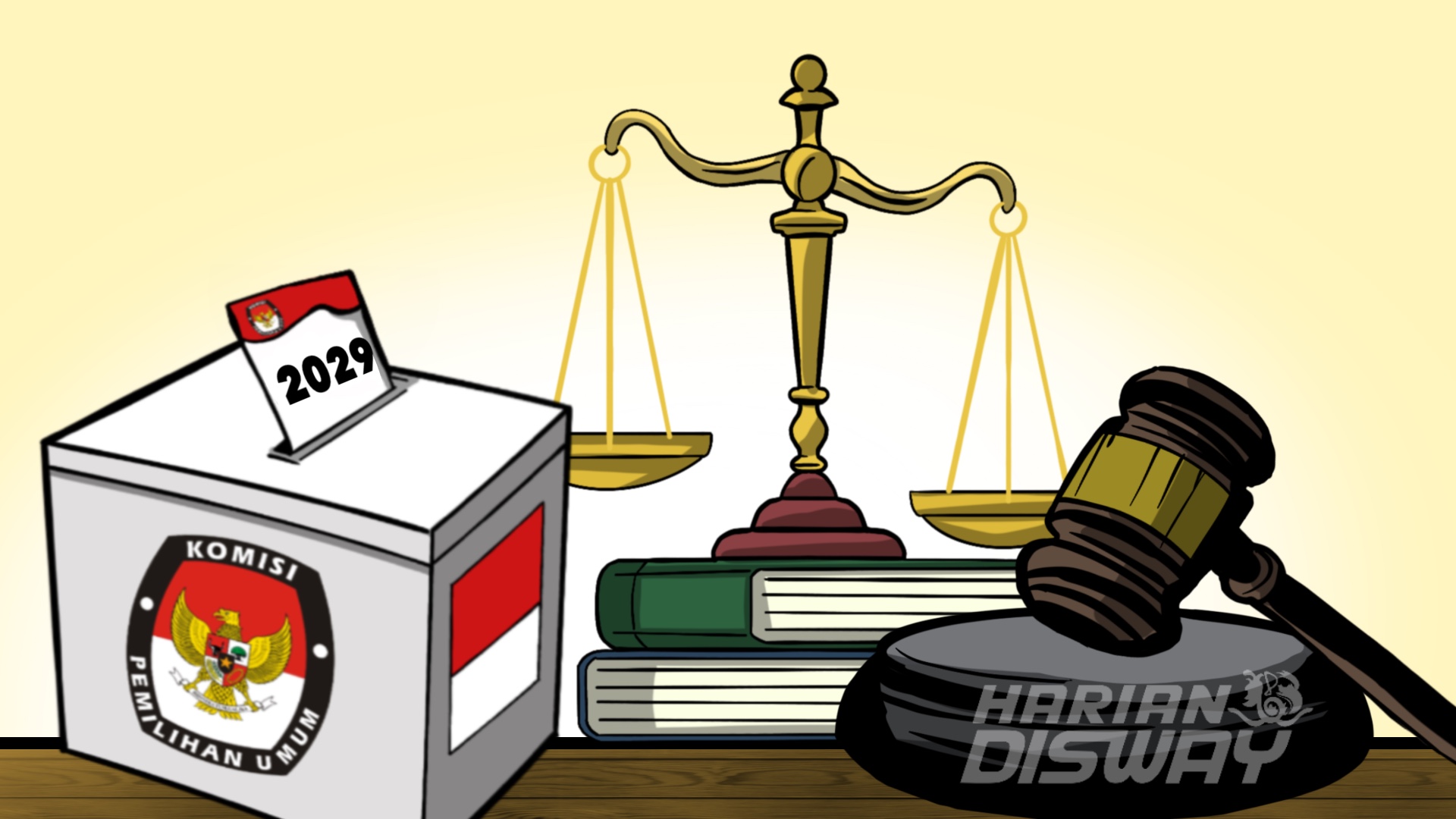
ILUSTRASI Menjaga Kewarasan Publik: Mengawal Transisi 2029 dari Jebakan ”Ritual” Hukum.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
DALAM kacamata antropologi, hukum sering kali tidak hanya bekerja sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai sebuah sistem simbol dan ritual. Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), palu hakim, dan lembaran putusan adalah artefak budaya yang memberikan legitimasi kepada tatanan sosial kita.
Namun, apa jadinya jika artefak-artefak suci demokrasi itu tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, tetapi sekadar ”mantra” untuk memuluskan hasrat kekuasaan?
Mencermati dinamika politik hukum pasca-Pilpres 2024, khususnya serangkaian putusan MK terkait ambang batas dan syarat usia pencalonan, tampak adanya pergeseran tektonik dalam budaya politik Indonesia.
BACA JUGA:Sentimen Pasar Pilpres
BACA JUGA:Urgensi Etika dalam Kampanye Pilpres
Fenomena itu sejatinya bukan sekadar sengketa pasal-pasal, melainkan sebuah transformasi perilaku elite yang berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi proyeksi Pemilu 2029. Kita sedang melihat normalisasi ”akrobat hukum” sebagai ritual politik baru yang kian wajar.
DESAKRALISASI KONSTITUSI: HUKUM SEBAGAI ALAT, BUKAN NILAI
Antropolog Clifford Geertz pernah memperkenalkan konsep Negara Teater. Yakni, kekuasaan dipertontonkan melalui ritual-ritual megah untuk memukau rakyat. Hari ini panggung teater itu bernama Mahkamah Konstitusi.
Elite politik kita tampaknya telah menemukan ”celah kebudayaan” baru: legitimasi kekuasaan tidak harus didapat murni dari keringat kampanye atau adu gagasan, tetapi bisa dipanen melalui rekayasa legal-formal di ruang sidang.
Putusan-putusan kontroversial belakangan ini menunjukkan gejala bahwa hukum sedang didesakralisasi. Ia diturunkan derajatnya dari values (nilai luhur penegak keadilan) menjadi tools (alat pertukangan kekuasaan).
Dalam antropologi politik, itu disebut sebagai instrumentalisasi pranata sosial. Bahayanya, ketika elite mempertontonkan bahwa aturan main bisa diubah di tengah pertandingan –atau bahkan sesaat sebelum peluit ditiup– masyarakat sedang diajari sebuah moralitas baru: ”segala cara itu sah, asalkan ada stempel pengadilannya”.
Jika kita proyeksikan ke Pemilu 2029, itu adalah sinyal bahaya. Jika pada 2024 kita terkejut dengan putusan yang meloloskan kandidat tertentu lewat revisi syarat usia, maka pada 2029, kita mungkin akan menghadapi situasi yang lebih chaotic.
Para aktor politik tidak akan lagi fokus membangun basis massa atau menyusun visi kebangsaan. Energi mereka akan habis untuk ”berperang” di meja hijau jauh sebelum pemilu dimulai: melobi tafsir konstitusi, mengutak-atik threshold, hingga merancang undang-undang yang didesain khusus (tailor-made) untuk memuluskan klan atau kelompok tertentu.
KEMBALI KE HUKUM RIMBA DALAM JUBAH DEMOKRASI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: