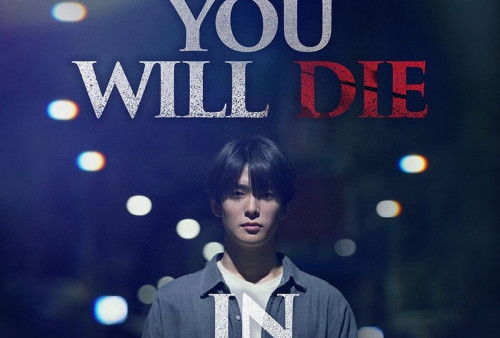Farel Prayoga

-Ilustrasi: Reza Alfian Maulana-Harian Disway-
FAREL PRAYOGA, penyanyi cilik asal Banyuwangi, sukses menggoyang Istana Merdeka. Tamu kehormatan, para menteri, dan beberapa jenderal yang mengikuti upacara 17 Agustus turun dari tribun kehormatan, lalu ikut berjoget bersama Farel yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke.
Jenderal Dudung terlihat asyik bergoyang, Sri Mulyani pun ikut turun menggoyang-goyangkan badan. Prabowo Subianto– yang biasanya serius– ikut turun ke bawah dan berjoget bersama hadirin lainnya.
Presiden Jokowi berdiri tesenyum senang di podium kehormatan, sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo bergoyang-goyang dari tempat duduknyi.
Suasana upacara yang biasanya serius dan tegang menjadi cair. Semua yang hadir ikut terhanyut dalam suasana. Bahkan, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo –yang sedang puyeng memikirkan kasus Ferdy Sambo– juga ikut bergoyang pelan-pelan dari tempat berdirinya di podium.
Ketika Farel selesai menyanyikan lagu pertama, ada permintaan dari audien supaya menambah satu lagu lagi. Jokowi yang ditawari lagu apa yang ingin didengar spontan menjawab Joko Tingkir. Rupanya Jokowi tahu lagu itu sedang viral dan banyak digemari publik.
Farel bersiap menyanyikan Joko Tingkir. Tapi, tim lapangan yang mengelilingi Farel terlihat saling berbisik-bisik, kemudian lagu itu batal dinyanyikan. Sebagai gantinya, Farel mengulangi lagi lagu Ojo Dibandingke.
Kalau saja Farel jadi menyanyikan Joko Tingkir, suasana akan makin meriah dan reaksi netizen akan makin heboh. Rupanya tim Istana khawatir lagu itu akan memicu kontroversi dan reaksi pro-kontra kalau dinyanyikan di depan Jokowi. Musababnya, beberapa kalangan mengecam lagu Joko Tingkir karena dianggap melecehkan ulama.
Penampilan Farel menjadi simbol desakralisasi terhadap istana yang dilakukan Jokowi. Selama ini Jokowi mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari rakyat jelata, wong cilik, dan istana bukan tempat yang skaral seperti pada era Presiden Soeharto.
Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, istana adalah locus kekuasaan yang sakral. Soeharto menempatkan dirinya sebagai penguasa Jawa yang mendapatkan kekuasaan dari pulung yang turun dalam bentuk wahyu kedaton. Wahyu tersebut sakral dan hanya turun kepada orang-orang pinilih, orang-orang yang terpilih.
Dalam konsep kekuasaan Max Weber, seseorang menjadi pemimpin karena mendapatkan mandat rakyat melalui pemilihan atau menjadi pemimpin karena karismanya diakui rakyat.
Seseorang juga bisa menjadi pemimpin karena mengeklaim mendapatkan wahyu kedaton dari dewa-dewa. Model kekuasaan itulah yang diterapkan di sistem mornarki atau kerajaan.
Sebagai penganut kejawen tulen, Pak Harto meyakini kekuasaannya merupakan wahyu. Karena itu, ia memperlakukan kekuasaannya sebagai sesuatu yang skaral. Semua atribut kekuasaan kepresidenan juga menjadi objek sakralisasi. Kekuasaan adalah sakral dan istana adalah sakral.
Tidak sembarang orang bisa memasuki istana. Ketika diizinkan masuk ke istana, seseorang tidak boleh bertindak sembarangan. Bernyanyi dan berjoget di istana tidak akan diizinkan Soeharto karena bertentangan dengan sifat istana yang sakral.
Kondisi itu berubah total setelah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur melakukan dekonstruksi terhadap kekuasaan dan istana. Sebagai aktivis demokrasi yang berlatar belakang kiai, Gus Dur langsung melakukan desakralisasi dengan membongkar tatanan birokratis yang ditinggalkan Pak Harto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: