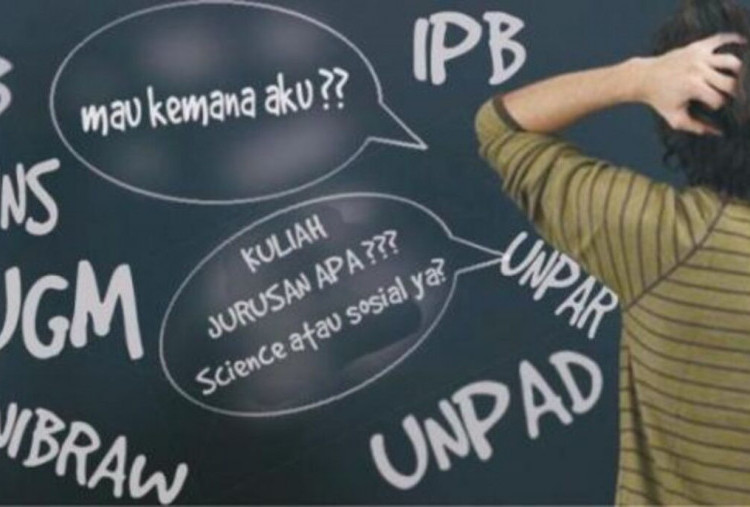Hakim Juga Manusia

ILUSTRASI Hakim Juga Manusia.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
BACA JUGA:Hakim Pemberi Vonis Bebas Minta Penjara Dekat Keluarga
BACA JUGA:Skandal Suap Hakim Vonis Lepas CPO, 3 Hakim Diduga Terima Rp 22,5 Miliar
Kedua, ada kelemahan sistemik dalam dunia peradilan. Kita tahu bahwa sistem hukum di Indonesia kerap digerogoti budaya ”kebersamaan dalam dosa”. Lihat saja pengakuan hakim Ali Muhtarom: ”Saya ikut karena kebersamaan.”
Kebersamaan yang semestinya bermakna sinergi untuk kebenaran berubah menjadi solidaritas dalam penyimpangan.
Itulah yang dalam psikologi disebut moral disengagement, yaitu ketika seseorang menormalisasi kesalahan karena ”semua orang juga melakukannya”. Dalam suasana seperti itu, korupsi menjadi budaya organisasi, bukan lagi pelanggaran personal.
Ketiga, ada ketimpangan sosial dan materialisme. Seorang hakim mungkin setiap hari mengadili perkara bernilai miliaran rupiah, sedangkan gajinya tidak sebanding dengan tanggung jawab dan risiko moralnya. Ketika kesejahteraan tak sepadan dengan tanggung jawab, integritas mudah tergadaikan.
Namun, tentu saja, rendahnya penghasilan tak pernah bisa dijadikan alasan untuk menukar keadilan dengan uang. Itu hanya menjelaskan sebab, bukan membenarkan akibat.
Lebih dalam dari semua itu, sebenarnya kita sedang menyaksikan krisis nurani. Ketika rasa takut kepada Tuhan lenyap, hukum tak lagi bersandar pada nilai, tetapi hanya pada pasal. Padahal, keadilan sejati tak lahir dari teks undang-undang semata, tetapi dari hati yang bersih dan nurani yang jernih.
Hakim yang kehilangan kesadaran spiritual sejatinya telah kehilangan arah moral. Mereka lupa bahwa setiap palu yang diketukkan tak hanya tercatat di risalah sidang, tapi juga di catatan langit.
Kita sering berkata, ”hakim juga manusia”. Benar, mereka manusia. Tapi, menjadi hakim bukanlah profesi biasa. Itu adalah amanah ilahiah yang menuntut standar moral di atas rata-rata manusia. Sebab, jika keadilan bisa dibeli, yang miskin akan selalu kalah sebelum beperkara.
Kasus itu seharusnya menggugah kesadaran seluruh bangsa, terutama lembaga peradilan, untuk melakukan pembenahan serius.
Rekrutmen hakim harus menekankan integritas dan kepribadian, bukan sekadar kecerdasan hukum.
Pembinaan rohani dan etika profesi harus menjadi bagian permanen dalam kultur peradilan.
Kesejahteraan hakim mesti dijaga agar mereka tidak ”takjub saat melihat banyak uang”.
Dan, yang tak kalah penting, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar ruang gelap di balik toga bisa diterangi cahaya transparansi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: