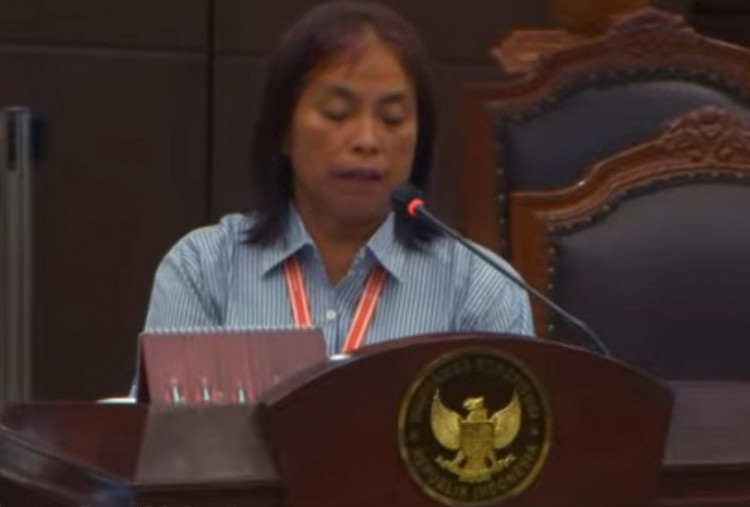Kugadaikan Kotaku: Ketika Laut dan Hidup Dipertaruhkan
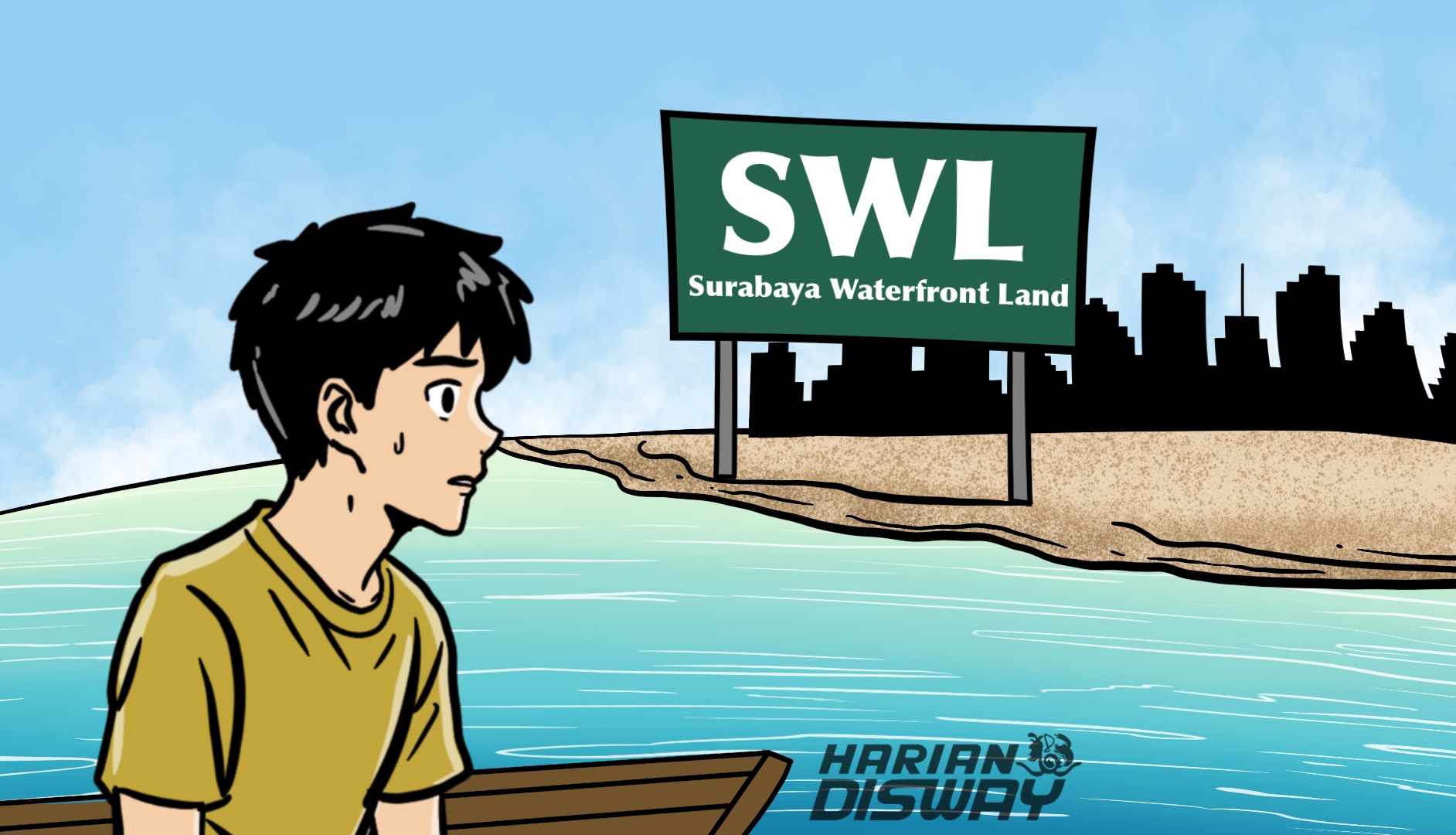
ILUSTRASI Kugadaikan Kotaku: Ketika Laut dan Hidup Dipertaruhkan.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Semua ini adalah warisan budaya tak benda yang telah membentuk identitas kolektif kami sebagai manusia maritim selama berabad-abad. Menghapus laut berarti menghapus identitas dan sejarah kami.
Hutan bakau –pelindung alami kami dari rob dan badai– akan ditebang atas nama ”kemajuan”. Bakau, bagi kami, adalah pagar hidup, tempat anak cucu kami belajar tentang ekologi pesisir.
Hilangnya bakau bukan hanya krisis lingkungan: ia adalah perampasan ruang belajar dan ruang spiritual kami. Apa yang tersisa dari kota ini jika laut dan rakyatnya tak lagi punya tempat?
PEMBANGUNAN YANG TAK PERNAH BERTANYA
Kami tidak anti pembangunan. Namun, kami bertanya: pembangunan untuk siapa?
Sejak diumumkan, proyek ini berjalan nyaris tanpa suara kami. Sosialisasi dilakukan setengah hati. Konsultasi publik hanya formalitas. Sementara itu, izin dan investasi terus berjalan. Suara-suara penolakan dianggap gangguan.
Paradigma pembangunan itu menganggap kami, warga pesisir, sebagai objek yang harus dipindahkan, bukan subjek yang berhak menentukan nasib ruang hidup mereka. Kami disingkirkan dari peta perencanaan, seolah-olah kami adalah anomali yang harus ditertibkan demi wajah kota yang clean dan elite.
Padahal, yang kami tuntut sederhana: jangan hilangkan rumah kami. Jangan diam-diam ambil laut kami. Jangan jadikan hidup kami angka statistik demi keuntungan mereka yang tak pernah menginjakkan kaki di kampung kami.
Pembangunan adalah proses budaya, bukan sekadar proyek fisik. Jika pembangunan menghancurkan kebudayaan, menghapus identitas, dan merampas local wisdom, ia adalah penghancuran peradaban terselubung.
Surabaya sebagai kota maritim modern seharusnya merangkul, bukan meminggirkan, identitas maritimnya yang sesungguhnya: para nelayan dan penjaga pesisir.
KOLONIALISME RUANG DAN GUGATAN ATAS HAK BUDAYA
Di balik jargon ”pengembangan kawasan” dan ”iklim investasi”, tersimpan realitas yang timpang: mereka yang paling terdampak justru paling sedikit dilibatkan.
Kami melihat itu sebagai bentuk kolonialisme ruang (spatial colonialism) gaya baru: laut dan tanah kami diambil demi elite dan investor, sedangkan kami disuruh ”beradaptasi” atau ”pindah” –seolah-olah cara hidup kami hanyalah relik masa lalu yang harus dikorbankan demi ”kemajuan” versi mereka.
Kami menuntut pengakuan atas hak kultural dan ekologis kami.
Apakah itu keadilan? Apakah itu pembangunan? Jika kota ini benar-benar milik semua, ruang harus dibagi secara adil. Termasuk ruang laut. Termasuk hak kami untuk tinggal, mencari makan, dan hidup layak di kota tempat kami lahir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: