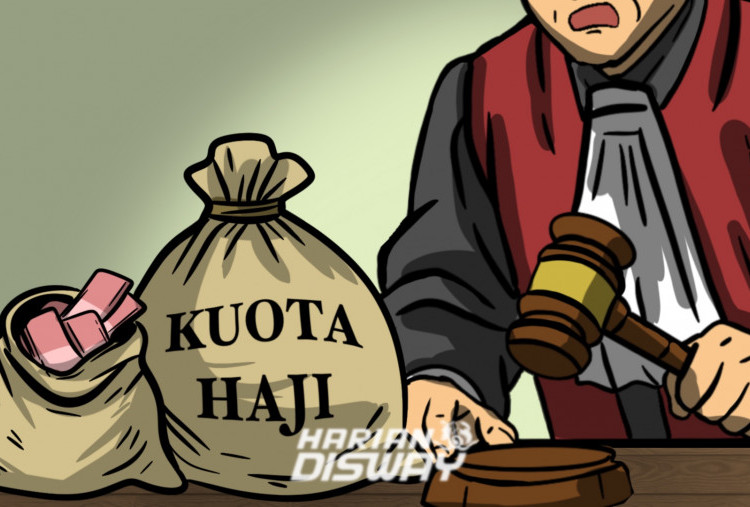Nikah Siri: Antara Keimanan, Cinta, dan Ironi Hukum Perkawinan

Ilutrasi banyak sisi dari nikah siri.-Artificial Intelligence-

--
Utiyafina Mardhati Hazhin, S.H., M.H. *)
Fenomena nikah siri kembali mencuri perhatian publik setelah kasus Inara Rusli menyeret isu poligami tanpa pencatatan. Di tengah hiruk-pikuk konflik rumah tangga selebritas, publik seolah diingatkan bahwa praktik perkawinan siri tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu, tetapi dapat muncul bahkan di lingkaran figur publik sekalipun.
Persoalan ini bukan untuk menilai siapa yang menjadi korban atau pelaku, melainkan untuk menegaskan bahwa pengabaian terhadap kewajiban pencatatan perkawinan berpotensi membuka ruang kerentanan bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak.
Antara Kesalehan dan Ketidakpastian Hukum
Perkawinan bukan hanya sekadar kontrak sosial, legalitas status hubungan suami istri, atau pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Ia juga memiliki dimensi aspek ubudiyah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
Dalam Islam, perkawinan dianggap sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, banyak pasangan merasa cukup menikah secara agama, sehingga menganggap pencatatan negara tidak dipandang sebagai hal yang esensial. Perkawinan yang tidak dicatatkan inilah yang kemudian dikenal dalam masyarakat sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan.
BACA JUGA:Nikah Siri, Kepala Dusun Ditangkap
BACA JUGA:Sudah Nikah Siri, Wakil Rakyat Terpikat Pemandu Lagu
Secara etimologis, kata "siri" berasal dari bahasa Arab sirr, yang berarti "rahasia". H.A. Wasit Aulawi (1996) menjelaskan, nikah siri merujuk pada pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan.
Sebagian masyarakat memilih jalan ini karena dorongan religius, ingin segera "menghalalkan hubungan", atau karena cinta yang didorong oleh keinginan untuk menghindari dosa. Namun, kesalehan dan cinta sering kali berhenti pada tataran emosional dan kurang diimbangi dengan logika kesadaran hukum.
Padahal, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menekankan bahwa pencatatan bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hak-hak sipil. Tanpa pencatatan, perempuan tidak dapat mengajukan cerai, menuntut nafkah, memperoleh harta bersama, maupun membuktikan status anak.
Dalam pandangan agama, pernikahan justru sebenarnya dianjurkan untuk diumumkan. Hadis Nabi memerintahkan agar perkawinan diumumkan dan dirayakan melalui walimah sebagai bentuk deklarasi publik. Dengan demikian, pencatatan oleh negara sejatinya dapat dipahami sebagai bentuk modern dari prinsip keterbukaan akad yang ditekankan oleh syariat.
BACA JUGA:Lesti Kejora - Rizky Billar Sudah Menikah Siri Sejak Awal Tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: