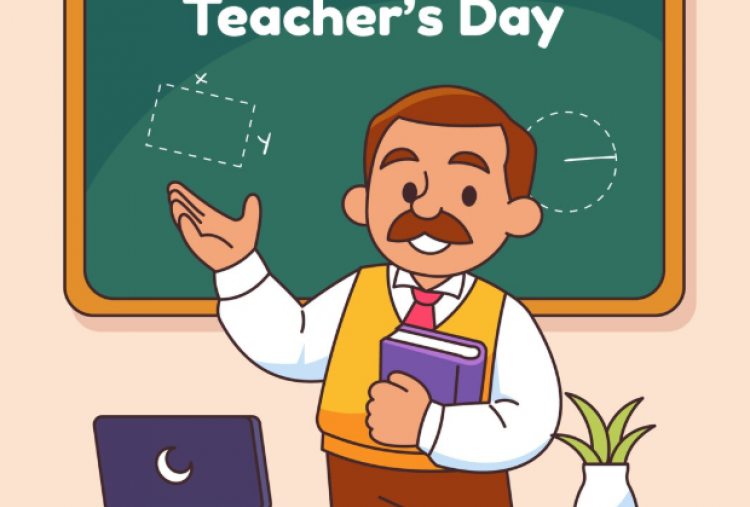Kerusakan Ekologis sebagai Kezaliman Struktural

ILUSTRASI Kerusakan Ekologis sebagai Kezaliman Struktural.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
PEMBANGUNAN hampir selalu datang dengan nada optimisme. Ia hadir sebagai janji kemajuan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. Namun, di balik derapnya yang cepat, PEMBANGUNAN menyimpan satu pertanyaan mendasar: seberapa jauh ia masih berpijak pada amanah untuk menjaga kehidupan, bukan sekadar mengakumulasi manfaat jangka pendek?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika pembangunan pariwisata bergerak masuk ke ruang-ruang ekologis yang rapuh, seperti Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
Kawasan itu bukan sekadar lanskap indah, melainkan juga sistem ekologis yang menyimpan air, menopang kehidupan, dan menjaga keseimbangan alam bagi masyarakat luas.
BACA JUGA:Mandat Jurnalisme Warga di Tengah Krisis Ekologis
BACA JUGA:Mengendus Jejak Gelap Rent-Seeking di Balik Bencana Ekologis
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut menghadapi tekanan pembangunan yang kian intensif.
Pariwisata dan pemanfaatan sumber daya air skala besar membawa konsekuensi ekologis yang sering kali tidak langsung terlihat, tetapi bersifat akumulatif dan jangka panjang: berkurangnya cadangan air tanah, perubahan bentang alam, dan meningkatnya kerentanan lingkungan dan sosial.
INDUSTRI PARIWISATA DAN BATAS ETIKA
Pariwisata kerap dipersepsikan sebagai sektor ”bersih” dan ramah lingkungan. Namun, asumsi itu menjadi problematis ketika diterapkan pada wilayah dengan daya dukung yang terbatas. Karst bukan ruang kosong yang bebas dimodifikasi, melainkan sistem alam yang bekerja dalam keseimbangan yang halus dan saling terkait.
BACA JUGA:Greenflation, dari Basa-basi Politis ke Kesadaran Ekologis
BACA JUGA:Renungan Harlah Ke-101 NU: Meneguhkan Gerakan Ekologis NU
Masalah muncul ketika pembangunan dikendalikan oleh logika yang seragam. Semua wilayah diperlakukan sama, semua potensi dianggap layak dikapitalisasi. Legalitas administratif lalu dijadikan tolok ukur utama: selama izin terpenuhi, pembangunan dianggap sah, sedangkan dampak ekologis diposisikan sebagai risiko yang dapat dinegosiasikan.
Di titik itulah pembangunan mulai kehilangan dimensi etiknya. Kerusakan lingkungan tidak selalu hadir secara dramatis. Ia sering muncul secara senyap: kualitas air menurun, ruang hidup menyempit, dan beban risiko perlahan dialihkan kepada masyarakat sekitar. Pertanyaan keadilan pun mengemuka: siapa yang menikmati manfaat dan siapa yang menanggung dampaknya?
Dalam tradisi pemikiran Islam, situasi semacam itu sejak lama dibaca sebagai fasād fī al-arḍ. At-Tabari memaknai fasād bukan hanya sebagai kejahatan moral individual, melainkan juga segala tindakan yang merusak kemaslahatan umum dan keteraturan hidup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: