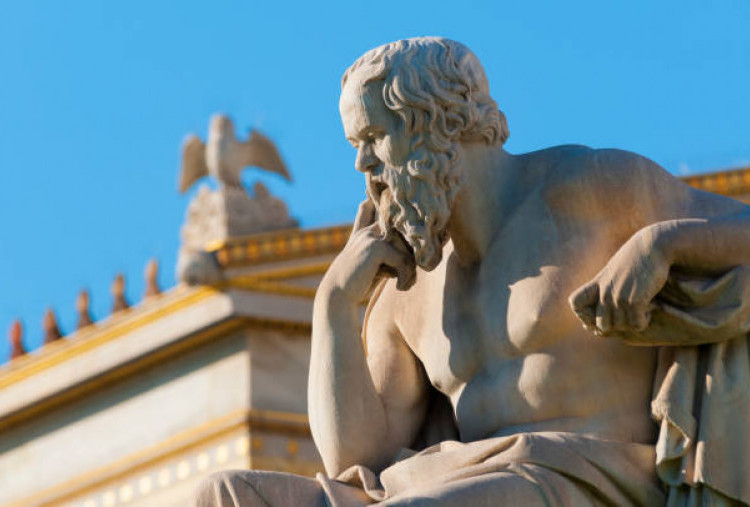Menghidupkan Ilmuwan yang Kritis dan Berpihak

ILUSTRASI Menghidupkan Ilmuwan yang Kritis dan Berpihak -Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Ilmuwan semacam itu kerap menjadikan kompetensinya sebagai ”alat stempel” atau pembenaran epistemologis bagi kekuasaan dan kebijakan yang lahir darinya, alih-alih menggunakannya untuk kemaslahatan umat.
BACA JUGA:Cendekiawan dalam Pusaran Politik (Tanggapan Artikel Prof Biyanto)
REALITAS SOSIAL-POLITIK KEKUASAAN DAN SIKAP ILMUWAN
Dalam sepuluh tahun terakhir, para ilmuwan dan intelektual Indonesia dihadapkan pada realitas sosial-politik dan ekonomi yang makin problematik, terutama dengan tumbuh suburnya praktik politik dinasti dan oligarki.
Fenomena itu terlihat jelas dalam Pemilu 2024, yang menjadi bukti nyata bagaimana politik dinasti dan oligarki beroperasi dan bekerja jauh dari nilai etika dan moralitas demokrasi.
Masa transisi demokrasi adalah periode krusial bagi sebuah negara, menentukan apakah akan melangkah menuju konsolidasi demokrasi atau justru kembali ke pola otoritarianisme gaya baru. Negara-negara yang baru keluar dari rezim otoritarian sering kali menghadapi tantangan itu.
Demokrasi, ironisnya, dapat dihancurkan oleh pemimpin yang terpilih melalui mekanisme legal-formal seperti pemilu. Awalnya, pemimpin tersebut mungkin dianggap demokratis dan diharapkan dapat merawat serta membangun ekosistem demokrasi yang berkualitas.
Namun, banyak yang kemudian berubah menjadi demagog politik, mengandalkan ketakutan, intimidasi, dan fanatisme untuk mempertahankan kekuasaannya.
Dalam catatan global, fenomena itu memiliki preseden. Levitsky dan Ziblatt dalam buku How Democracies Die (2019) mencatat tokoh-tokoh seperti Benito Mussolini, Adolf Hitler, Hugo Chavez, Alberto Fujimori, dan Getulio Vargas.
Semuanya meraih kekuasaan melalui mekanisme politik yang sah, tetapi kemudian mengancam demokrasi.
Fenomena serupa kini menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.
Meski berasal dari produk demokrasi elektoral modern, kepemimpinan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir justru menunjukkan kecenderungan menuju otoritarianisme gaya baru. Demokrasi Indonesia hampir kehilangan prinsip check and balance karena lemahnya oposisi.
Dengan arsitektur politik-kekuasaan yang mapan di parlemen (DPR dan MPR) maupun kabinet, Jokowi berhasil menciptakan pagar kekuasaan yang kuat, menjadikannya makin kebal dari dinamika politik.
Penurunan kualitas demokrasi Indonesia telah menjadi perhatian lembaga internasional. Freedom House mencatat penurunan skor demokrasi Indonesia dari 62 poin menjadi 53 poin pada 2019–2023. Reporters Without Borders (RSF) juga mencatat penurunan kebebasan pers, dengan skor turun dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: